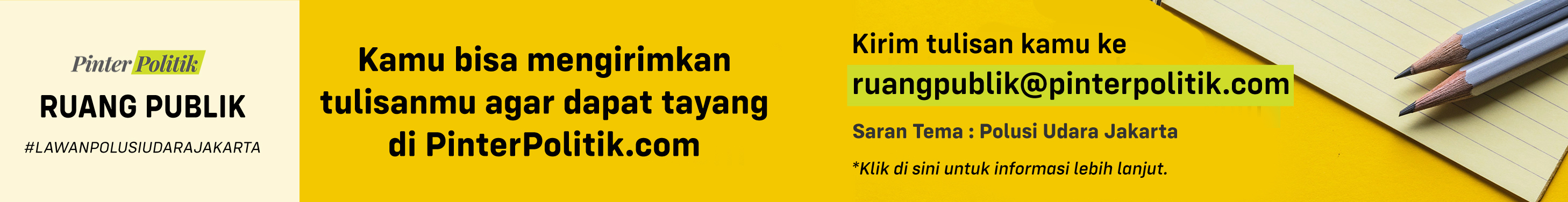Berbagai penembakan dan kekerasan banyak terjadi di negara-negara Barat. Peristiwa-peristiwa tersebut bisa jadi berkaitan dengan adanya kebangkitan gerakan supremasi rasial kelompok putih di Eropa dan Amerika Serikat (AS).
PinterPolitik.com
Akhir Juli dan awal Agustus 2019 ini dunia kembali diguncang oleh rentetan penembakan massal yang terjadi di Amerika Serikat (AS), seperti yang terjadi di Gilro Garlic Festival, di El Paso, Texas, dan di Dayton, Ohio. Rentetan kejadian ini mempertegas ada pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah AS untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa.
Ada tiga alasan paling populer yang disebut-sebut menjadi penyebab bagi kejadian-kejadian tersebut, yakni regulasi senjata yang terlalu longgar, faktor mental, dan asupan ideologis. Regulasi bisa ditambal dengan mekanisme atau prosedur baru mengenai kepemilikan senjata yang lebih ketat. Gangguan jiwa, meskipun sulit, namun bisa diatasi dengan memberikan pendampingan dan pelayanan psikologis terhadap penduduk, khususnya anak-anak dan remaja yang berada di usia rentan secara berkala.
Masalah ini kemudian akan menjadi sangat sulit ditanggulangi oleh pemerintah AS ketika sudah menyangkut aspek ideologis. Hal ini karena ideologi merupakan landasan atau cara berpikir seseorang dalam menyikapi sesuatu.
Artinya, ideologi bersifat abstrak dan sangat sulit untuk diidentifikasi sampai sesuatu yang dipicu oleh ideologi itu sendiri terjadi. Pemikiran juga tidak bisa dipenjarakan, terlebih lagi di negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan berpendapat seperti AS.
Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan mencoba menjelaskan ideologi apa yang menjadi penyebab rentetan penembakan ini terjadi, dan mengidentifikasi sebab-sebab utama berkembangnya ideologi ini di negara-negara Barat.
Great Replacement Theory
The Great Replacement Theory – teori konspirasi rasial dari kelompok nasionalis kulit putih yang dipopulerkan oleh Renaud Camus – telah menjadi perbincangan publik pada Maret 2019 lalu ketika terjadi penembakan di beberapa masjid di Selandia Baru. Pada saat itu, sesaat sebelum melancarkan aksi penembakan brutalnya, Brenton Tarrant lebih dulu menyebarkan manifestonya yang menyebut The Great Replacement Theory di akun media sosialnya.
Rosa Schwartzburg dalam tulisan opininya di The Guardian menjelaskan bahwa, secara sederhana, ada dua poin pokok dari teori ini. Pertama, identitas ‘barat’ sedang dalam ancaman akibat gelombang imigrasi yang masif dari negara-negara non-Eropa atau non-kulit putih yang nantinya dinilai dapat menggeser populasi orang kulit putih.
Kedua, perubahan ini telah dimainkan sedemikian rupa oleh ‘kelompok bayangan’ (shadowy group) sebagai bagian dari rencana besar mereka untuk menguasai dunia dimana mereka akan menciptakan masyarakat yang homogen secara rasial.
Pemikiran ini kemudian terus berkembang dan menjadi landasan ideologis para ekstremis supremasi kulit putih yang melakukan aksi pembunuhan brutal. Anders Breivik, pembunuh massal di Norwegia dalam manifestonya mengungkapkan ketakutannya akan terjadinya pergantian populasi kulit putih menjadi kulit coklat dan hitam karena kedatangan imigran keturunan Afrika Utara dan Timur Tengah di Eropa.
Hal ini dilanjutkan oleh Brenton Tarrant, penembak massal Christchurch yang dalam manifestonya juga menyinggung tentang angka kelahiran. Manifesto Tarrant inilah yang kemudian menginspirasi pelaku pembunuhan massal di El Paso.
Secara garis besar, penulis berargumen bahwa ada dua hal yang menjadi penyebab utama berkembangnya ideologi supremasi kulit putih ini, yaitu tingginya angka imigran non-Barat ke negara-negara Barat dan populisme sayap kanan oleh politisi negara-negara Barat untuk mendapatkan dukungan elektoral.
Suburnya Angka Imigran
Revolusi Musim Semi Arab (Arab Spring), kehadiran ISIS, serta konflik yang tak henti-hentinya terjadi di Timur Tengah membuat angka pengungsi dan imigran dari negara-negara terdampak di Timur Tengah ke negara-negara Eropa melonjak. Puncaknya, pada tahun 2015, Eropa mengalami apa yang dikenal sebagai krisis pengungsi, di mana lonjakan angka imigran terjadi secara luar biasa. Menurut data International Organization for Migration (IOM) yang dihimpun oleh BBC pada tahun 2015, tercatat sekitar 1.006.000 orang melintasi perbatasan Uni Eropa secara ilegal.
Hal serupa terjadi di AS. Sejak lama, AS telah menjadi negara tujuan utama para imigran dan pengungsi dari seluruh dunia. Iming-iming “land of freedom” membuat AS menjadi negara yang terlihat paling menarik dibandingkan dengan negara lainnya bagi orang yang terjebak perang, krisis politik-ekonomi, hingga kriminalitas di negara asalnya. AS dipandang sebagai sebuah negeri utopia yang akan membangunkan mereka dari mimpi buruk yang mereka alami sehari-hari.
Menurut data Census Bureau, pada tahun 2016, angka imigran (legal dan ilegal) yang berasal dari Timur Tengah, Amerika Latin (selain Meksiko), Asia, dan Afrika Sub-Sahara yang tiba di AS meningkat secara signifikan. Sebaliknya, imigran yang berasal dari Meksiko, Eropa, dan Kanada justru menurun atau bahkan berkurang.
Lebih lanjut, Census Bureau memaparkan bahwa saat ini ada sekitar 43,7 juta imigran yang berada di AS, dan memprediksi akan terus melonjak dalam tahun-tahun yang akan datang. Pada 2060, diprediksi 78,2 juta imigran akan bermukim di negeri Paman Sam. Menurut data PBB, AS menjadi negara penampung imigran terbanyak pada 2015 dengan 48,2 juta jiwa – sekitar 15% dari populasi warga negaranya.
Tingginya angka imigran non-kulit putih di dua wilayah dengan mayoritas kulit putih menimbulkan reaksi negatif di kalangan masyarakat. Menurut penelitian lembaga think–tank asal Belgia, Bruegel, pada Januari 2018, ada dua faktor utama yang menjadi sebab negara Eropa sulit menerima imigran, yaitu ada anggapan dari masyarakat Eropa bahwa para imigran mendapatkan fasilitas dan keuntungan dari yang seharusnya didapat dan adanya sentimen bahwa imigran yang tiba merupakan orang-orang buangan tanpa keterampilan.
Sementara itu, penelitian Pew Research Center mencatat ada kenaikan signifikan pada tahun 2019 dari jumlah Republicans – sebutan untuk pendukung dan konstituen Partai Republik –yang menganggap AS mengambil resiko kehilangan identitas nasionalnya jika terlalu terbuka dengan imigran.
Berbagai dampak negatif dan sentimen yang muncul di tengah-tengah masyarakat memicu terjadinya berbagai aksi penolakan dan diskriminasi terhadap imigran. Masyarakat kulit putih merasa terancam dengan kehadiran imigran yang semakin hari terus bertambah dan membaur di lingkungan mereka. Hal ini diperparah dengan faktor kedua, yakni populisme sayap kanan yang digaung-gaungkan para politisi untuk mencapai kepentingan elektoral mereka.
Populisme Sayap Kanan
Status quo pada saat ini semakin panas dengan komentar-komentar pedas para politisi sayap kanan di negara-negara Barat yang terus mengobarkan semangat anti-imigran. Scott Morrison, Geert Wilders, Donald Trump, Matteo Slavini hingga Boris Johnson adalah beberapa politisi yang sukses merebut perhatian publik dengan mengobarkan semangat sayap kanan yang anti-imigran dan rasis. Bahkan, nama-nama di atas – kecuali Wilders – sukses merebut tampuk kepemimpinan di negaranya masing-masing.
Morrison, yang terpilih sebagai PM Australia pada 2018 lalu, pada tahun 2014 sempat terlibat dalam kontroversi mengenai pelarangan imigran di Nauru dan Manus yang hendak menuju ke pantai Australia. Pada saat bersamaan, Presiden AS Trump sudah begitu terkenal dengan retorika-retorika dan kebijakan anti-imigrannya.
Pelarangan untuk masuk ke AS dari beberapa negara mayoritas Muslim dan mengambil langkah luar biasa dengan melewati keputusan kongres demi meloloskan proposal pembangunan tembok di perbatasan dengan Meksiko yang ditujukan untuk mengentikan imigran dari Amerika Selatan adalah di antaranya.
Sementara itu, populisme juga bangkit di berbagai negara besar Eropa seperti Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Belanda, Austria, dan sebagainya. Bahkan partai dan pemimpin yang berkuasa di negara-negara tersebut – kecuali Prancis dan Belanda – adalah partai-partai berhaluan sayap kanan yang dengan nyaring menyuarakan semangat anti-imigran. Partai Front Nasional di Prancis dan PVV di Belanda meskipun gagal menjadi penguasa namun mengalami peningkatan suara yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Tumbuh suburnya partai sayap-kanan di berbagai negara Barat ini seolah-olah menjadi wadah bagi masyarakat yang kian jengah terhadap kebijakan imigrasi yang dianggap telah mengancam negaranya dan etnisnya. Berbagai pernyataan-pernyataan kontroversial dari tokoh politik yang rasis juga dapat menyulut penganut ideologi white supremacist yang seolah teramini untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap manusia dengan identitas yang berbeda.
Pertanyaannya kemudian, apa bahaya yang ditimbulkan gerakan ini bagi dunia dalam tahun-tahun mendatang?
Tulisan milik M. Hafizh Nabiyyin, mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Potensi Utama.
“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.