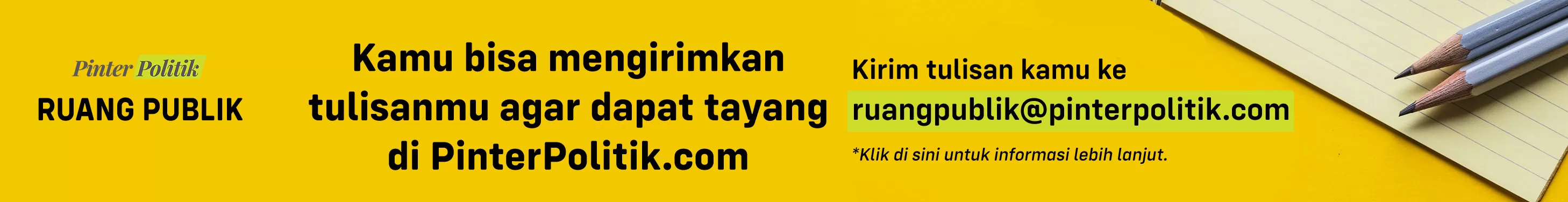Gelombang penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 bisa jadi menunjukkan minimnya keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakannya. Mungkin, hal ini menunjukkan nasib ruang publik yang semakin tertutup.
PinterPolitik.com
“The parliament no longer is an ‘assembly of wise men chosen as individual personalities by privileged strata, who sought to convince each other through arguments in public discussion on the assumption that the subsequent decision reached by the majority would be what was true and right for the national welfare.’ Instead it has become the ‘public rostrum on which, before the entire nation (which through radio and television participates in a specific fashion in this sphere of publicity), the government and the parties carrying it present and justify to the nation their political program, while the opposition attacks this program with the same openness and develops its alternatives.” – Jürgen Habermas
Berbagai persoalan pelik menerpa babak akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. Di antaranya, terdapat permasalahan kemanusiaan di Papua, pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai bermasalah, serta – yang paling memantik reaksi masyarakat – penetapan revisi Undang-Undang (UU) KPK yang dinilai terburu-buru, tidak mendengar aspirasi publik, dan berpotensi melemahkan taji pemberantasan korupsi di Indonesia.
Atas beberapa peristiwa tersebut, banyak pihak menuding pemerintahan Jokowi telah mencederai cita-cita demokrasi Indonesia pada era Reformasi – terutama dalam konteks pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta jaminan negara atas hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat.
Beberapa bulan berselang, situasi politik di Indonesia mulai mereda. Satu demi satu instrumen pemerintahan periode 2019-2024 juga telah terbentuk. Sebanyak 575 orang wakil pilihan rakyat telah duduk nyaman di bangku empuk senayan. Kabinet berjumlah 34 orang pembantu presiden juga telah disumpah dan bertitah akan bekerja beriringan demi kemajuan bangsa.
Namun, dengan berbagai persoalan yang telah disebutkan tadi, layakkah kita menyemai optimisme pada pemerintahan mendatang untuk merawat demokrasi ini? Mari kita berkaca sebentar.
Polemik RUU KPK dan Pembukaan Ruang-ruang Demokrasi
Akhir September lalu, berbagai lapisan masyarakat yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi publik dalam merespons penetapan revisi UU KPK. Di samping itu, proses pengesahan undang-undang KPK juga dinilai terburu-buru dan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.
Diketahui, proses pengesahan revisi UU KPK dilakukan hanya dalam kurun waktu 12 hari. Pembahasan mengenai revisi ini tiba-tiba muncul pada Rapat Paripurna pada 5 September dan disahkan pada 17 September.
Revisi UU KPK juga tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2019. Hal ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran.
Masyarakat yang sepatutnya menjadi pihak sentral dalam pengambilan kebijakan pun dinegasikan menjadi pelanggan yang ‘terima jadi’, tanpa dilibatkan dalam proses penggodokan. Masyarakat ‘ditelantarkan’ tanpa informasi, tanpa ruang untuk didengarkan, hingga akhirnya peraturan dibentuk tanpa berkonsultasi pada konsensus publik.
Masyarakat seharusnya sejak awal diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi politik mereka secara publik dengan jaminan bahwa aspirasi tersebut akan diserap oleh sistem politik yang ada. Melalui kesepahaman yang terbentuk melalui proses diskusi di dalam ruang demokratis tersebut, para penguasa kemudian dapat membentuk kebijakan/peraturan yang telah ‘teruji’ oleh opini publik.
Ramai-ramai mengenai revisi UU KPK merupakan contoh solid bahwa alur komunikasi politik secara bottom-up di Indonesia mengalami penyumbatan, entah secara sengaja maupun tidak. Ruang aspirasi masyarakat seharusnya tidak terbatas pada demonstrasi di jalan.
Namun, jauh sebelum itu, dibutuhkan pembukaan ruang-ruang demokrasi di mana publik sebagai pemangku kepentingan dan penguasa sebagai pembentuk kebijakan dapat bertemu untuk mencapai konsensus mengenai sebuah aturan/kebijakan. Perlu dipahami bahwa keterlibatan masyarakat dalam demokrasi bukan hanya lima tahun sekali melalui pemilihan umum. Bukan juga hanya melalui kegiatan unjuk rasa ke jalanan.
Masyarakat harus sadar akan hak mereka untuk dapat mendiskusikan pendapat mereka secara publik dan mempersoalkan segala tema yang relevan agar proses pembentukan kebijakan menjadi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Fransisco Budi Hardiman dalam bukunya yang berjudul Demokrasi Deliberatif menuturkan bahwa ruang demokratis – di mana para warga negara dapat menyatakan opini, kepentingan, dan kebutuhan mereka secara diskursif – adalah gagasan pokok ruang publik politis (political public sphere).
Konsep public sphere (ruang publik) sendiri merupakan sebuah gagasan yang diperkenalkan oleh salah satu pemikir politik paling penting generasi kedua mazhab Frankfurt, yakni Jürgen Habermas. Konsep public sphere yang dijelaskan oleh Habermas pada dasarnya mengacu kepada sebuah domain dalam kehidupan sosial manusia dimana opini publik dapat terbentuk.
Opini tersebut kemudian harus dijadikan acuan bagi penguasa agar terus-menerus melakukan konsultasi dengan publik ketika mengambil keputusan mengenai kemaslahatan bersama. Antonius Galih Prasetyo dalam tulisannya yang berjudul Menuju Demokrasi Rasional menuturkan bahwa ruang publik memainkan peran yang vital dalam penguatan demokrasi, yakni sebagai ruang yang dihidupi oleh masyarakat sipil dan berfungsi sebagai intermediasi antara negara dengan individu privat. Melalui ruang publik, politik yang dijalankan dapat dikontrol dan diperiksa secara saksama melalui nalar publik.
Lantas, siapa yang memiliki tanggung jawab untuk membentuk ruang demokratis untuk menampung dan menyerap aspirasi publik tersebut?
Tanggung Jawab Siapa?
DPR dan partai politik mungkin adalah dua pihak yang turut bertanggung jawab. Apakah mereka telah menjalankan tugas tersebut?. Dilansir dari situsnya, salah satu tugas DPR adalah untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Serupa dengan tugas DPR tersebut, Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
DPR dan Partai Politik memiliki tugas sebagai intermediaris/perantara antara publik dan penguasa. Mereka seharusnya bertindak sebagai ‘pengeras suara’ rakyat yang aspirasinya perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan.
Belakangan ini, muncul wacana DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk membuat “alun-alun demokrasi” di kompleks gedung DPR/MPR. Tujuannya tak lain untuk memfasilitasi ruang aspirasi publik yang ingin melakukan unjuk rasa.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa “alun-alun demokrasi” tersebut dibuat agar masyarakat bisa melakukan unjuk rasa secara langsung di dalam kompleks parlemen. Mereka juga dijanjikan bisa bertemu langsung dengan pimpinan DPR dan akan difasilitasi untuk bertemu pejabat yang menjadi sasaran unjuk rasa.
Bamsoet menyebutkan bahwa alun-alun demokrasi ini dibuat agar kegiatan demonstrasi tidak mengganggu fasilitas umum seperti menutup jalan tol. Meski demikian, rasanya perlu dipahami kembali bahwa ruang aspirasi publik tidak sepatutnya dipandang sempit sebagai kegiatan demonstrasi semata.
Keterlibatan publik harus lebih dari itu. Jauh sebelum itu, publik harus dilibatkan dalam segala bentuk pembentukan peraturan yang memiliki konsekuensi terhadap kemaslahatan publik. Ruang-ruang publik dan saluran aspirasi harus dibuka selebar-lebarnya.
Keputusan politik yang menyangkut kemaslahatan publik mutlak harus berkonsultasi dengan opini publik. Kegiatan jajak pendapat dalam pembentukan peraturan/kebijakan harus dilakukan secara rutin dan transparan.
Forum-forum diskusi antara publik dan penguasa harus dilakukan secara terbuka, inklusif, dan egaliter. Publik tidak harus selalu “berpanas-panasan” dan berteriak-teriak kepada wakil rakyat terhormat agar dapat didengar. Kami yakin wakil rakyat tidak semanja itu.
Tulisan milik Avicena Farkhan Dharma, mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Brawijaya.
“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.