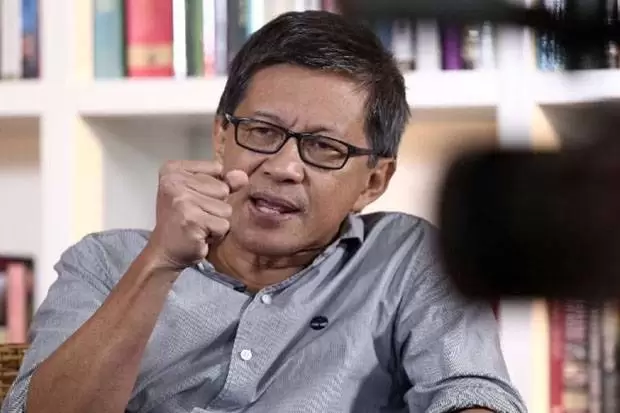Melanjutkan pernyataan Natalius Pigai, pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa politik Indonesia dipenuhi dengan buzzer pemerintah yang membuat demokrasi tidak berdiri dengan tegak. Apakah ini hanya pernyataan sinis seorang oposisi?
“We live in a world where there is more and more information, and less and less meaning.” – Jean Baudrillard, sosiolog Prancis
Mungkin judul artikel ini cukup provokatif tetapi bukan itu poinnya. Ada sebuah pertarungan yang berusaha diungkap, yakni percaturan politik yang penuh dengan citra-citra. Pada tahun 1964, dalam bukunya Understanding Media: The Extension of Man, Marshall McLuhan memberikan peringatan yang sayangnya saat itu banyak diabaikan.
Secara cukup mengejutkan, ilmuwan asal Kanada itu menyebut yang terpenting dari pesan justru bukanlah pesan itu sendiri, melainkan medium yang digunakan untuk mengantarkannya. “Medium adalah pesan,” ungkapnya. Setelah berdekade-dekade karyanya dikritik dan diabaikan, kemunculan internet pada tahun 1990-an menempatkan karya McLuhan sebagai nubuat.
Dalam bukunya Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital yang terbit pada tahun 2017, Ross Tapsell memberikan penjelasan penting atas pengaruh internet dan teknologi komunikasi massa terhadap demokrasi Indonesia.
Menurut Tapsell, media baru (new media) dan media sosial (medsos) memberikan dua perubahan penting yang dapat dilihat sebagai dua sisi mata koin. Di satu sisi, ini melahirkan oligarki baru yang mengepakkan sayap bisnisnya di industri media. Sisi ini yang Tapsell sebut sebagai oligarki media.
Sementara sisi lainnya adalah harapan. Menurut Tapsell, mungkin untuk pertama kalinya masyarakat mendapatkan akses, kesempatan, dan kapabilitas yang besar untuk menandingi kekuatan dan pengaruh elite. Melalui media sosial, cukup dengan ketikan jari, narasi tandingan dapat dihadirkan untuk menggugat ketidakadilan.
Tarik Ulur Pendulum
Dua sisi mata koin itu dapat dilihat dari pernyataan aktivis HAM Natalius Pigai dan pengamat politik Rocky Gerung. Pada 26 Januari, bertolak dari artikel The Guardian pada 23 Juli 2018, Pigai menyebut dirinya adalah korban dari buzzer pemerintah.
Artikel berjudul ‘I felt disgusted’: inside Indonesia’s fake Twitter account factories itu menjelaskan soal buzzer politik di Indonesia yang mulai masif digunakan sejak Pilkada DKI Jakarta 2017. Penulisnya, Kate Lamb, menyebut baik kubu pro dan kontra Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sama-sama menggunakan buzzer sebagai senjata politik.
Di kubu kontra, ada Muslim Cyber Army (MCA) yang menggunakan ratusan akun palsu dan anonim untuk menyebarkan konten rasis agar Ahok tidak dipilih. Sementara di kubu pro Ahok, Lamb mencontohkan salah satu tim buzzer yang diketuai sosok bernama Alex. Tim buzzer ini dibayar sekitar US$ 280 per bulan untuk mengunggah 60-120 kali konten dalam sehari di berbagai akun media sosial palsu mereka.
Pada 31 Januari, Rocky menyebut artikel The Guardian tersebut memberi pesan bahwa politik Indonesia penuh dengan kecurangan. Lanjutnya, hadirnya buzzer merupakan penyebab turunnya indeks demokrasi di Indonesia. Bertolak dari The Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia pada 2020 memang menurun dari 6,48 menjadi 6,30. Ini adalah yang terendah dalam 14 tahun terakhir.
Di titik ini, mungkin ada yang memandang sinis pernyataan Pigai ataupun Rocky, entah itu karena ketidaksukaan personal ataupun menilai keduanya terlalu berlebihan. Namun, Tapsell memberi penjelasan penting yang perlu untuk diperhatikan.
Menurut Tapsell, new media telah membawa bisnis media ke arah baru, yang sayangnya membuat industri ini menjadi arena kekuasaan oligark yang memiliki kapital berlimpah. Pasalnya, tidak seperti media tradisional yang hanya memproduksi koran, new media harus memiliki berbagai infrastruktur mahal yang tidak mungkin dimiliki oleh media-media kecil. Selain itu, Tapsell menyoroti terdapat konsentrasi kantor media yang berpusat di Jakarta, yang mana ini membuat isu regional Jakarta seolah menjadi isu nasional.
Ada pula statistik-statistik menarik, seperti hampir setengah cuitan harian di Indonesia ternyata berasal dari Jakarta. Artinya, produksi narasi nasional pada dasarnya ditentukan oleh kepentingan elite di ibu kota.
Lanjut Tapsell, new media kemudian membawa babak baru, di mana pemilik media memiliki kekuatan politik yang signifikan. Pemilik media seperti Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dan Hary Tanoesoedibjo, misalnya, menjadi aktor politik aktif yang bahkan memiliki partai politik.
Bertolak dari gagasan McLuhan, yakni “medium adalah pesan”, Tapsell menyebut media arus utama telah menjadi arena vital pergulatan kepentingan politik di Indonesia.
Kendati demikian, seperti yang disebutkan sebelumnya, sisi koinnya tidak hanya satu. New media juga dilihat Tapsell melahirkan harapan. Fenomena Arab Spring, yakni gelombang unjuk rasa dan protes di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara yang dimulai sejak 18 Desember 2010, merupakan contoh nyata.
Gerakan ini memanfaatkan media sosial, seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Skype, untuk mengorganisir, berkomunikasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap usaha-usaha menekan dan penyensoran Internet oleh pemerintah.
Di Indonesia, Tapsell melihat media sosial telah menjadi medium untuk melawan dominasi oligarki media. Meskipun hanya bermodal media sosial, kesatuan narasi telah mampu menjadi ancaman, atau setidaknya membuat oligark media tidak menjadi tiran tak terusik. Para oligark media mengamati secara berkala narasi-narasi masyarakat yang sekiranya berpotensi membahayakan kepentingan dan mengganggu status quo-nya.
Hadirnya dua sisi koin itu dapat kita lihat sebagai tarik ulur pendulum. Bola pendulum tidak pernah berdiam di satu sisi. Ia akan terus berayun ke kanan dan ke kiri, tergantung dari kekuatan mana yang mendorong atau menariknya.
Hidupnya Diskursus Politik
Well, di titik ini ada satu pesan yang harus diperhatikan. Terlepas dari tepat tidaknya kritik Rocky Gerung ataupun pihak-pihak lainnya, kritik itu harus dibaca sebagai upaya melawan pendulum oligarki media. Dan memang terbukti, suara-suara keras mereka telah menghidupkan diskursus politik nasional.
Terkait ini, sangat menarik untuk melihat gagasan seorang filsuf politik bernama Chantal Mouffe. Mouffe menegaskan bahwa politik itu dibangun di atas perbedaan “kita” dan “mereka” – us vs them. Menariknya, Mouffe justru melihat konflik sebagai suatu hal yang positif. Dengan adanya konflik dan konfrontasi, itu menjadi penanda bahwa demokrasi yang lekat dengan budaya dialog dan kritisisme tengah hidup.
Simpulan ini Mouffe tarik dari fakta bahwa masyarakat adalah entitas yang begitu plural. Dengan kata lain, jika tidak terjadi konflik, maka entitas plural itu tengah dibungkam atau dicoba untuk diseragamkan.
Ilmuwan politik Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, menyebut pembungkaman tersebut dilakukan oleh negara-negara otoriter seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Untuk merespons era digital yang memberi akses berpendapat yang luas, Tiongkok telah melakukan penyensoran ketat untuk menekan sekecil mungkin perlawanan politik.
Sebagai penutup, menarik untuk mengutip penjelasan Donny Gahral Adian dalam bukunya Demokrasi Substansial: Risalah Kebangkrutan Liberalisme. Menurut Donny, pluralitas adalah kondisi sebuah ruang publik yang menjadi tempat setiap orang menyingkapkan keunikannya dan sekaligus mengakomodasi keunikan orang lain dalam mengambil keputusan bersama.
Indonesia yang merupakan entitas plural sekiranya termanifestasi ke dalam diskursus politik yang hidup dan menggairahkan. Tanpa adanya dorongan diskursus dari masyarakat, arus narasi hanya akan menjadi panggung bagi para oligarki media dan elite politik.
Namun, tentu perlu dicatat, ada perbedaan antara kebebasan berpendapat dengan ujaran kebencian. Seperti kekhawatiran Fukuyama, jangan sampai media sosial justru menjadi medium untuk mengentalkan polarisasi, ketegangan, dan kekerasan di tengah masyarakat. (R53)