Tidak diragukan lagi, situasi politik Indonesia saat ini sedang dirundung keterpecahan. Kontes politik di ibukota ternyata berdampak signifikan terhadap kesadaran kebangsaan secara keseluruhan di Indonesia.
pinterpolitik.com
[dropcap size=big]G[/dropcap]erimis sore ini bercampur asap-asap kendaraan, menu lain untuk cita rasa polusi di ibukota. Saat ini memang sedang waktunya orang pulang kantor, tak heran Jakarta sedang macet-macetnya.
Mirna berdiri di ujung tangga, menjauh dari rintik-rintik hujan. Tangannya sedari tadi sibuk mengutak-atik handphone sambil sesekali melihat ke langit, bertanya-tanya kapan hujan ini akan berhenti.
Ah, hujan ini tak mau berhenti. Jemputan tak kunjung datang. Mana disuruh cepat pulang lagi. Ia sebenarnya enggan pulang cepat, tetapi pesan singkat dari ibunya siang tadi mau tidak mau membuatnya harus segera pulang.
“Mir, nanti pulang cepat ya, malam ini ada kumpul bersama dengan tim sukses untuk pilkada putaran kedua”, begitu pesan singkat yang dikirim ibunya.
Ah, males banget. Tapi, karena bapak dan ibu adalah tim sukses utama, dan calon yang didukung sangat berjasa bagi keluarga mereka, mau tidak mau ia harus ikut. Sebenarnya, dalam hati, Mirna kurang mendukung calon pemimpin dukungan keluarganya itu. Ia lebih menyukai calon lain yang secara kinerja menurut dia lebih bagus.
Namun, Mirna tak punya pilihan lain. Ia teringat ketika pada pemilihan presiden lalu ia sempat mogok bicara dengan ibunya sendiri gara-gara berbeda pilihan politik. Ya ampun, politik benar-benar bisa membuat orang dewasa jadi seperti anak-anak. Apalagi sekarang menjelang pilkada putaran kedua, kalau ia tetap kukuh dengan pilihan politiknya, bisa-bisa jadi berantem sama si ibu. Toh nanti ibu nggak tahu siapa yang aku pilih di TPS. Mirna tersenyum memikirkan hal itu.
“Mbak… mbak.. woi mbak”. Mirna terkaget dengan sosok pria bermotor di depannya.
“Mbak Mirna, ya? Yang pesan ojek online tadi?” tanya pria itu.
“Iya, Pak. Betul”, jawab Mirna.
“Ayo atuh mbak, mumpung hujannya belum lebat. Jangan senyum-senyum sendiri terus”, kata pria itu sambil menyodorkan helm hijau di tangannya.
Mirna tersenyum dan meraih helm itu. Ah, si bapak tau aja. Mungkin ngalamin juga berantem sama istrinya gara-gara Pilkada.
“Ayo, pak”, kata Mirna setelah mengenakan helm dan duduk di atas jok motor. Ah, demokrasi, bikin pecah keluarga orang saja.
Motor butut itu pun berlalu ke jalanan, beradu dengan macetnya jam pulang kantor. Ah, ibukota, kapan kau berhenti macet dan banjir.
Pilkada Rasa Pilpres
Tidak diragukan lagi, situasi politik Indonesia saat ini sedang dirundung keterpecahan. Kontes politik di ibukota ternyata berdampak signifikan terhadap kesadaran kebangsaan secara keseluruhan di Indonesia. Tidak heran jika banyak yang menyebutnya dengan istilah ‘Pilkada Jakarta rasa Pilpres’ – merujuk pada situasi keterpecahan yang terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2014 lalu.
Kisah Mirna yang berbeda pandangan politik dengan keluarganya mungkin merupakan salah satu contoh dari sekian banyak keluarga di ibukota yang ‘terpecah’ karena pandangan politik. Ada yang bapak dan ibunya ‘putih-putih’, sementara anaknya ‘kotak-kotak’. Ada yang suaminya ‘putih-putih’, eh istrinya ‘kotak-kotak’. Ada yang satu keluarganya ‘putih-putih’, eh keluarga besar lainnya ‘kotak-kotak’. Orang bisa berbeda pandangan politik sekalipun dalam satu keluarga. Namun demikian, hal ini adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam demokrasi. Setiap orang bebas untuk menentukan pilihan politiknya.
Hanya saja, keterpecahan kali ini sudah mulai mengarah pada hal-hal yang prinsipil dan fundamental, misalnya tentang semangat kebangsaan dan keberagaman – sesuatu yang berbeda dengan yang terjadi pada tahun 2014 lalu. Sehari yang lalu kita menyaksikan aksi masa di depan gedung DPR, melakukan demonstrasi dan protes, menuntut agar Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diberhentikan dari posisinya sebagai gubernur Jakarta. Tuntutan lain yang disuarakan adalah agar pemerintah berhenti melakukan kriminalisasi terhadap para ulama.
Degradasi Kebhinekaan dan Kebangsaan?
Demonstrasi ini tidak lain merupakan kelanjutan dari kasus penistaan agama yang menjadi warna dominan dalam kontestasi politik ibukota selama hampir 6 bulan terakhir ini. Hal yang patut disayangkan adalah karena isu agama seolah menjadi begitu dominan dalam konstes politik. Isu kebhinekaan, toleransi dan saling menghormati seolah terdegradasi oleh nafsu untuk berkuasa.
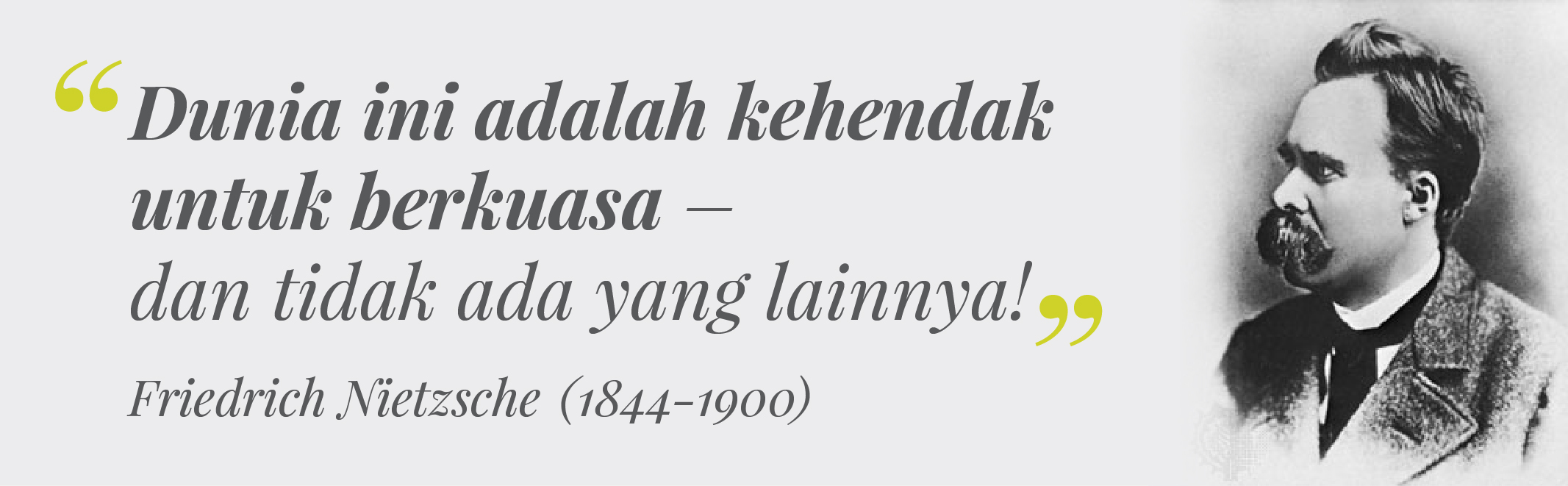
“Dunia ini adalah kehendak untuk berkuasa – dan tidak ada yang lainnya!” Demikianlah kata Friedrich Nietzsche (1844-1900) – seorang filsuf eksentrik dari Jerman. Kehendak untuk berkuasa seolah membutakan mata dan bisa mengalahkan segala prinsip-prinsip, norma, serta nilai-nilai yang dihormati dalam masyarakat. Maka, tidak heran, nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan keberagaman dengan begitu mudah dipermainkan demi satu tujuan: kekuasaan, dan bagaimana mempertahankannya. Tentang hal tersebut, Thomas Hobbes (1588-1679) pernah mengatakan: “Nafsu yang terkuat dalam diri manusia adalah nafsu untuk mempertahankan dirinya”. Mempertahankan kekuasaan adalah salah satu nafsu terkuat manusia.
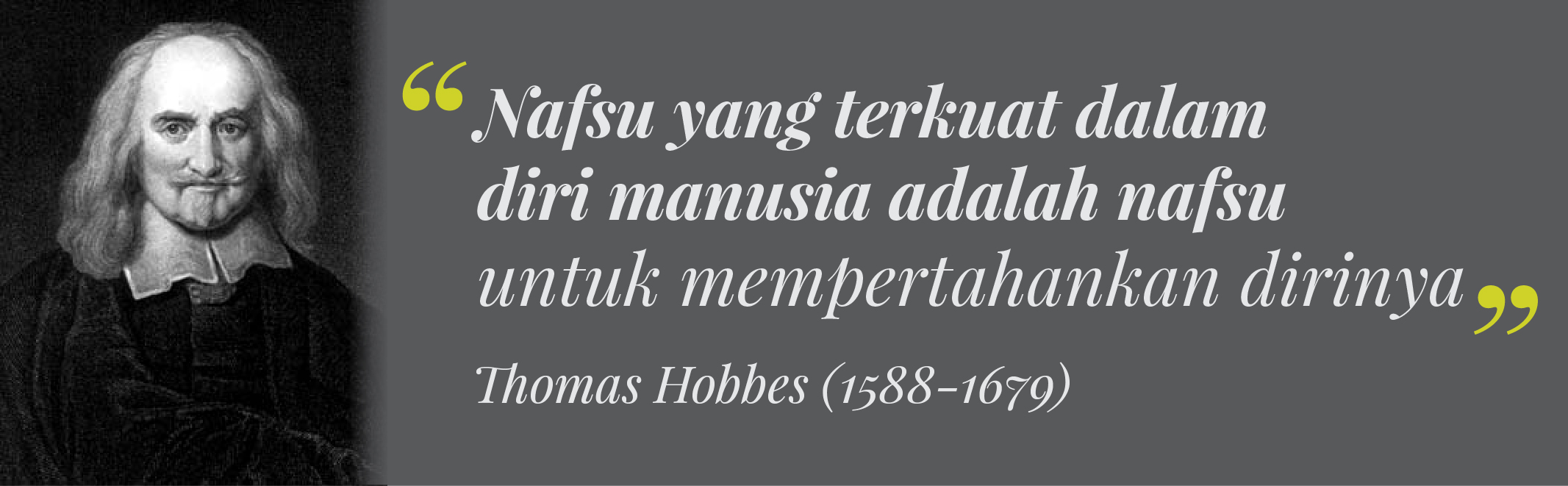
Hal ini tentu patut disayangkan karena negara ini – dengan segala perjuangan bersimbah keringat dan darah – dibangun atas fondasi penghargaan terhadap nilai-nilai tersebut. Lalu, apa boleh mengatakan bahwa saat ini kita sedang mengalami degradasi nilai-nilai kebangsaan? Perlu penelitian sosial yang mendalam untuk membuktikan hal tersebut. Namun, secara kasat mata kita bisa menyaksikan hal tersebut sedang terjadi, secara perlahan dan mulai berdampak serius.
Politik dan Keterpecahan
Situasi keterpecahan mungkin bisa dimaknai sebagai keadaan ketika masyarakat terbagi dalam dua kubu sebagai akibat perbedaan pandangan politik. Perbedaan pandangan politik ini bisa terjadi terkait pilihan dukungan terhadap salah satu calon dalam konstes politik seperti pemilihan kepala daerah maupun kepala negara.
Apa yang saat ini terjadi di Amerika Serikat (AS) bisa dianggap sebagai keterpecahan sosial sebagai akibat dinamika yang terjadi dalam kontestasi politik domestik. Pasca kemenangan Donald Trump, masyarakat AS terpecah dalam dua kubu. Ada yang begitu keras mendukung Trump, sementara mayoritas yang lain – karena Hillary Clinton memenangkan popular vote – menentang segala kebijakan Trump. Apalagi, kebijakan-kebijakan Trump juga semakin kontroversial, misalnya terkait pelarangan imigran dari negara tertentu, dan lain sebagainya.
Keterpecahan politik di AS tidak melahirkan rekonsiliasi pasca Trump dilantik sebagai presiden. Hal yang sama juga pernah terjadi di Indonesia pasca pilpres 2014. Presiden Jokowi dan saingannya dalam pilpres, Prabowo Subiyanto mungkin sudah menunjukkan semangat rekonsiliasi itu. Tetapi, untuk beberapa lama kita menyaksikan keterpecahan politik di DPR dalam tajuk koalisi Indonesia Hebat yang mendukung pemerintahan Jokowi versus koalisi Merah Putih dari partai-partai oposisi.
Saat ini panggung politik ada di ibukota Jakarta. Keterpecahan politik bisa dilihat dari perbedaan-perbedaan yang terus mengemuka, bahkan mulai mengancam nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan. Kalau dibandingkan dengan situasi yang terjadi di tahun 2014, apa yang terjadi di Jakarta kali ini – walau dalam proporsi yang lebih kecil – membutuhkan restorasi dan rekonsiliasi yang lebih serius. Situasi yang terjadi di Amerika Serikat adalah gambaran bahwa rekonsiliasi itu tidak terjadi. Tentu saja kita tidak ingin hal tersebut berlarut-larut dan mengancam nilai-nilai kebangsaan kita.
Restorasi atau Rekonsiliasi: dari Kaisar Meiji, Trump, Hingga Jokowi
Lalu, mana yang sebenarnya kita butuhkan di Jakarta? Rekonsiliasi atau restorasi? Dua istilah ini memang memiliki arti yang mirip, namun berbeda makna. Restorasi mempunyai akar kata dari bahasa Latin ‘restaurare’ yang berarti ‘mengembalikan ke keadaan semula atau keadaan awal’. Sementara rekonsiliasi mempunyai akar kata dari bahasa Latin ‘reconsiliare’ yang berarti ‘memperbaiki’ atau ‘membuat jadi baik kembali’ atau ‘mengembalikannya pada harmoni dan keteraturan’.
Ada banyak contoh restorasi yang terjadi di dunia. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah restorasi Meiji di Jepang yang dilakukan oleh Kaisar Meiji (1852-1912). Restorasi yang dilakukan oleh kaisar Meiji ini mengakhiri zaman Edo atau zaman kekuasaan Shogunat Tokugawa yang berkuasa di Jepang antara tahun 1600 sampai 1800. Restorasi Meiji mengembalikan posisi kaisar sebagai sentral politik masyarakat Jepang, sama seperti yang terjadi sebelum sistem Shogunat mulai dilaksanakan pada abad ke-11. Jepang pun akhirnya memasuki masa kejayaan dan mengejar ketertinggalan dari bangsa barat.
Contoh lain yang cukup terkenal adalah Restorasi Manchu pada tahun 1917 yang digagas oleh Jenderal Zhang Xun untuk mengembalikan kekuasaan di Tiongkok kepada Dinasti Qing setelah Tiongkok masuk dalam era Republik Demokrasi pimpinan Sun Yat-sen (1866-1925).
Dalam konteks yang lebih kontemporer, slogan ‘Make America Great Again’ yang dipakai oleh Trump selama kampanye pilpres di Amerika Serikat merupakan program restorasi ala Trump. Trump ingin ‘mengembalikan’ kejayaan Amerika Serikat – entah dalam periode mana kejayaan yang dimaksudkan itu. Hanya saja, cita-cita restorasi ‘Make America Great Again’ ini tidak disertai rekonsiliasi untuk menggandeng pihak-pihak yang secara politik berseberangan. Akibatnya situasi keterpecahan politik dan sosial pun terjadi.
Di lain pihak, rekonsiliasi cenderung mengarah kepada upaya untuk kembali menciptakan kedamaian pasca pertikaian atau perbedaan pandangan. Contoh rekonsiliasi bisa dilihat dalam kasus konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM), konflik Ambon, ataupun Poso. Masyarakat secara bersama-sama melupakan segala peristiwa yang terjadi di masa lalu dan berusaha untuk bekerjasama membangun daerah.
Rekonsiliasi juga pada akhirnya terjadi juga pasca Pilpres 2014 lalu antara Jokowi dan Prabowo. Pilihan politik yang berbeda tidak harus menjadikan orang sebagai musuh satu dengan yang lainnya. Konsep rekonsiliasi juga bisa dilihat dalam fenomena aksi damai ‘412’ dengan membawa budaya kedaerahan dengan tajuk ‘Kita Indonesia’ untuk kembali merangkul masyarakat pasca demonstrasi besar-besaran pada hari sebelumnya. Memang hanya budaya kedaerahan yang bisa menyatukan masyarakat Indonesia.

Restorasi atau Rekonsiliasi Kebangsaan?
Restorasi adalah ‘proyek’ yang besar, sama seperti revolusi. Oleh karena itu, restorasi ada kalanya juga berujung pada pertumpahan darah – hal yang bisa dilihat dalam kasus Restorasi Inggris (1660) atau Restorasi Bourbon (1814-1830) di Perancis. Namun, hal itu bisa dihindari jika ada rekonsiliasi politik. Dengan kata lain rekonsiliasi merupakan jalan untuk mencegah zero sum game – sebuah istilah untuk menggambarkan situasi ada yang kalah dan ada yang menang dalam politik – dan menciptakan solusi yang menguntungkan dan mendamaikan bagi semua orang (win-win solution) dalam sebuah proses restorasi.
Dalam kaitannya dengan konsep kebangsaan, restorasi kebangsaan bisa diartikan sebagai upaya untuk melihat kembali konsep kebangsaan yang sama seperti yang digariskan oleh pendiri negara ini. Restorasi kebangsaan artinya upaya untuk mengembalikan konsep kebangsaan seperti pada zaman founding fathers negara ini.
Soekarno adalah bapak proklamator kita yang tegas dengan konsep kebangsaan Indonesia yang satu dari Sabang sampai Merauke. Namun, Soekarnoisme bercita-cita membawa Indonesia kepada sebuah masyarakat sosialis – konsep yang mungkin saat ini sulit diterima lagi di Indonesia. Oleh karena itu, restorasi kebangsaan perlu juga diarahkan pada semangat yang saat ini benar-benar cocok dengan Indonesia. Mungkin yang perlu direstorasi adalah semangat kebangsaannya.
Restorasi mungkin ide yang terlalu besar. Oleh karena itu, konsep rekonsiliasi mungkin adalah yang paling cocok untuk diterapkan saat ini, khususnya di Jakarta. Ketegangan politik kerap terjadi karena adanya persaingan yang tidak sehat antara kandidat dan calon yang ikut dalam kontestasi politik. Kampanye hitam, saling menjatuhkan satu sama lain, dan menyerang sisi personal kandidat merupakan beberapa contoh hal yang justru bisa memperkeruh perpecahan dalam masyarakat Jakarta. Isu SARA juga adalah hal yang sangat berpengaruh. Oleh karena itu, perlu ada rekonsiliasi politik dan kebangsaan untuk menyatukan kembali semua pihak yang terpecah belah.
Rekonsiliasi pasca Pilkada Jakarta
Presiden Jokowi saat ini memainkan peran yang sangat sentral dalam konteks rekonsiliasi kebangsaan. Sikap netral Presiden dalam pilkada serentak di seluruh Indonesia adalah hal yang patut diparesiasi. Hal ini penting untuk mencegah perpecahan yang lebih besar di dalam masyarakat.

Selain itu, apa yang dilakukan oleh Kapolri, Panglima TNI, dan pemuka-pemuka agama yang bersikap netral merupakan hal yang patut diacungi jempol. Sikap-sikap tersebut harus disertai dengan ajakan untuk menggandeng semua pihak yang terpecah belah sebagai akibat sikap politik mendukung pasangan tertentu.
Kita tentu ingat peristiwa pengeroyokan yang dilakukan terhadap seorang simpatisan calon tertentu beberapa waktu lalu yang ditengarai dilakukan oleh tetangganya sendiri. Hal ini tentu memprihatinkan. Jangan sampai, pilkada bisa membuat orang adu jotos, bahkan saling melukai dan membunuh. Jangan sampai pilkada membuat tetangga saling bermusuhan, suami memusuhi istri, anak memusuhi orang tua dan lain sebagainya.
Kisah Marni yang diem-dieman sama ibunya mungkin merupakan contoh yang harus diambil intisarinya. Saat ini bangsa kita butuh rekonsiliasi nasional! Mungkin semangat restorasi – seperti yang pernah diucapakan oleh Bapak Surya Paloh – adalah hal yang masih terlalu jauh. Tetapi, setidaknya kita bisa kembali melihat hal-hal yang lebih positif dari semua persaingan politik yang terjadi, bahwasanya bangsa ini terlalu besar untuk dipecah belah.
Oleh karena itu, tidak ada salahnya menggandeng kembali tetangga yang berbeda pilihan politik, baik yang ‘putih-putih’ maupun yang ‘kotak-kotak’ untuk sama-sama membersihkan selokan, biar tidak banjir di musim yang tidak bisa diprediksi ini, tentu maksudnya agar kembali rukun seperti dahulu.
Pancasila Harga Mati!
Gerakan anti kebhinekaan yang belakangan ini mencuat menimbulkan tanda tanya besar: apa sebenarnya yang sedang terjadi? Persoalan ini sebetulnya tidak akan muncul jika semua orang di negeri ini mengakuai Pancasila sebagai dasar negara dan harga mati. Oleh karena itu, perbedaan dan kebhinekaan tidak bisa diganggu-gugat lagi.
Hanya saja, masih banyak orang di negeri ini yang menginginkan Pancasila diganti, digusur, atau bahkan dihilangkan. Hal ini patut diwasapadai karena bagaimana pun juga, Pancasila adalah cerminan utama kehidupan bangsa. Hal ini juga memprihatinkan karena bisa saja ini berarti pendidikan Pancasila tidak diajarkan dengan benar di bangku sekolah – catatan lain untuk sistem pendidikan nasional.
Biarlah segala perdebatan tentang dasar negara terjadi hanya pada zaman menjelang kemerdekaan. Bangsa ini besar dan beragam, oleh karena itu selayakanya menghormati perbedaan. Jangan sampai Pilkada memecah belah masyarakat dan membuat orang terkotak-kotak dalam sekat yang kehilangan kepercayaan – bahkan membenci – Pancasila.
Rekonsiliasi kebangsaan untuk menyatukan kembali bangsa yang terpecah belah harus dilakukan. Perlu ada saling memaafkan dan melupakan berbagai pertikaian masa lalu dan melihat jauh ke depan untuk menghadapi tantangan-tantangan kebangsaan kontemporer demi cita-cita kebangsaan bersama.

Gus Dur pernah bilang: “Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejarahan kita yang tidak boleh kita lupakan sama sekali.” Oleh karena itu, apa salahnya memaafkan saudaramu sebangsa dan setanah air? Biarlah sejarah bangsa ini ditulis dalam tinta emas karena penghormatannya terhadap perbedaan. Apakah hal itu mungkin terjadi? (S13)




