Peretasan yang dilakukan terhadap sejumlah awak Narasi TV dapat sorotan publik. Bagaimana kita memahami ini dari kacamata politik?
Pada akhir bulan lalu, tepatnya dimulai sejak tanggal 23 September, sejumlah karyawan dan mantan karyawan Narasi TV mendapatkan serangan peretasan yang masif. Menurut kabar terbarunya, peretasan ini menyerang 31 awak Narasi dan tujuh eks-karyawan Narasi. Peretasan tersebut berupa pengambilalihan kontrol akun-akun media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp.
Sebagai catatan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebut serangan terhadap Narasi ini adalah serangan peretasan termasif dan termassal yang pernah terjadi kepada kalangan jurnalis di Indonesia.
Tidak hanya itu, kuasa hukum Narasi TV, Ade Wahyudin, membeberkan bahwa peretasan yang terjadi bahkan dilakukan lebih mendalam lagi, dengan adanya sisipan sebuah pesan berbunyi “DIAM atau MATI” ke dalam server situs web Narasi. Terlepas dari konteks apakah serangan ini dilakukan terhadap jurnalis atau tidak, yang jelas ancaman seperti itu adalah sesuatu yang sangat serius dan patut ditindak sebagaimana mestinya.
Menariknya, peristiwa peretasan ini terjadi tidak lama setelah Narasi TV sebelumnya menyoroti fenomena kehidupan hedonis polisi dan istrinya terkait kasus Ferdy Sambo. Meski proses penelusuran dalang di balik peretasan ini masih dilakukan, Najwa Shihab menduga dengan kuat bahwa serangan dilakukan oleh pelaku yang sama.
Sejumlah pihak menilai bahwa serang yang dilakukan terhadap Narasi TV adalah bukti nyata dari upaya pembungkaman kekebasan pers. Dan memang, di dalam sebuah negara demokrasi seharusnya kebebasan pers menjadi suatu hal yang perlu dijunjung tinggi.
Ini kemudian membawa kita ke pertanyaan penting, mengapa peristiwa semacam ini bisa terjadi? Apakah benar bahwa ini adalah tanda bahwa demokrasi kita sebenarnya sudah tercederai?

Pembungkaman = Kegagalan Demokrasi?
Salah satu Founding Fathers Amerika Serikat (AS), James Madison, pernah mengatakan bahwa kebebasan pers adalah benteng terkuat kemerdekaan. Negara atau siapa pun itu seharusnya tidak berhak menghalangi atau mengambil hak rakyat untuk berbicara, menulis, atau mempublikasikan perasaan mereka di media.
Meski terdengar mulia dan perlu diperjuangkan, konsekuensi menjalankan sebuah negara demokrasi justru sepertinya akan menghalangi realisasi kebebasan pers yang utuh. Ahli bahasa sekaligus filsuf ternama asal AS, Noam Chomsky, dalam tulisannya Consent Without Consent menilai bahwa ada sebuah paradoks besar yang terjadi dalam hampir setiap negara demokrasi modern. Paradoks itu diberi istilah Hume’s Paradox.
Paradoks ini terinspirasi dari pandangan filsuf Skotlandia bernama David Hume yang menyoroti peran pemerintah sebagai sebuah kelompok kecil yang mampu mengontrol kelompok besar yakni masyarakat. Namun, Chomsky membawanya lebih lanjut dengan menilai bahwa, setelah munculnya media massa, pandangan Hume tadi bisa dikembangkan menjadi sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa penggiringan dan pembungkaman opini justru akan lebih marak terjadi di sebuah negara demokrasi dibandingkan negara yang otoriter.
Umumnya, orang akan mengatakan bahwa pengontrolan pers pasti akan lebih sering terjadi di sebuah negara yang memiliki pemimpin diktator. Akan tetapi, Chomsky membantah argumen tersebut dengan mengatakan bahwa di dalam sebuah negara yang otoriter, pemerintah justru tidak akan berbuat banyak untuk membungkam rakyatnya karena rakyat sudah tahu jika mereka berani melawan pemerintah, maka pemerintah juga akan berani menghukum mereka dengan sangat tegas, bahkan berani membunuh.
Keadaan tersebut tidak terjadi dalam sebuah negara yang menjalankan sistem demokrasi. Karena masyarakat yang tinggal dalam sebuah negara demokrasi sudah dijejalkan pemahaman bahwa kebebasan berpendapat adalah sesuatu yang perlu dijunjung tinggi, mereka akan lebih berani menyuarakan pendapat yang berseberangan dengan pemerintah. Akibatnya, karena pemerintah negara demokrasi perlu terus menjaga kestabilan negara, secara ironis, mereka akan lebih banyak melakukan upaya pembungkaman dibanding negara diktatorial.
Pandangan dari Chomsky ini bisa kita jadikan sebagai landasan untuk tidak hanya memahami kenapa bisa terjadi upaya pembungkaman terhadap Narasi TV, melainkan juga gambaran besar kenapa kebebasan pers begitu sulit diterapkan, bahkan dalam sebuah negara yang menjalankan sistem demokrasi sekali pun.
Nah, terkait serangan peretasan ini sendiri, walau belum diidentifikasi siapa penyerangnya, pihak Najwa dan khalayak publik sudah bisa menduga bahwa ini dilakukan oleh seseorang dengan kekuatan yang kuat, dan mungkin terlibat dengan kasus Ferdy Sambo yang memang pernah dikritik Najwa. Tapi kira-kira kenapa secara spesifik mereka perlu melakukan sebuah “serangan”, seperti peretasan ini?
Well, relative deprivation theory dari Ted Robert Gurr sepertinya bisa menjelaskan hal itu. Robert menilai bahwa kekerasan bermotif politik – yang salah satunya adalah upaya peretasan – terjadi ketika seorang oknum dengan kekuatan besar tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk mengatur perilaku dari seseorang atau sesuatu yang memiliki kekuatan lebih lemah darinya.
Sederhananya, teori ini mengatakan bahwa serangan politik seperti yang dilakukan pada awak Narasi TV sebenarnya menunjukkan keputusasaan dari siapa pun itu yang melakukan serangan. Karena mereka tidak mampu mengubah sikap Narasi TV, maka kekerasan perlu dilakukan dengan harapan bahwa itu akhirnya akan berhasil mengubah pandangan para awak Narasi TV.
Namun, pertanyaannya kemudian adalah, dari pandangan para peretas, apakah serangan ini sudah dilakukan secara efektif?
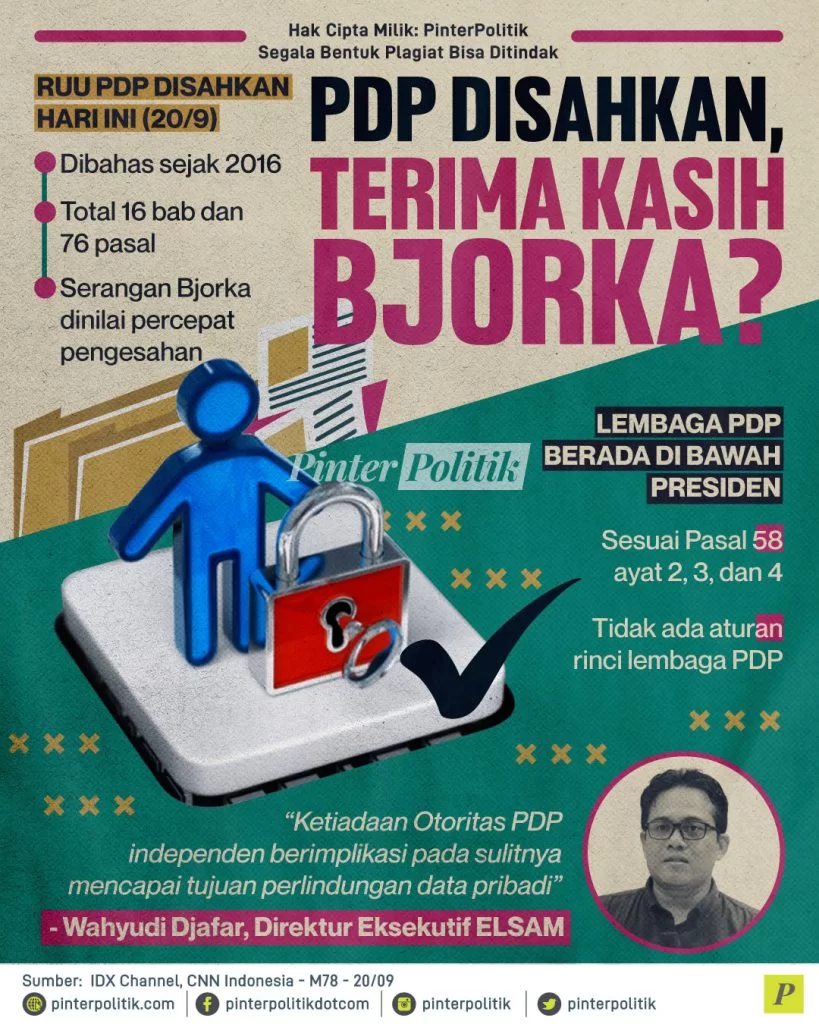
Bukan Ini Hasil yang Diharapkan?
Kalau kita melihat perkembangannya, kita bisa lihat bahwa ada yang menarik dari dampak serangan peretasan yang dilakukan terhadap Narasi TV.
Alih-alih sukses membuat Narasi TV diam dan membuat publik merasa takut, peretasan ini justru menghasilkan sesuatu yang benar-benar berlawanan. Publik malah jadi sadar bahwa ada upaya pembungkaman dan mereka justru terus mendukung Narasi TV agar tetap melemparkan kritik-kritik pedas kepada segala macam tindakan ketidakadilan.
Fenomena ini sangat sesuai dengan sesuatu yang disebut Streisand Effect – sebuah istilah yang diberikan kepada upaya-upaya yang memiliki tujuan menutup-nutupi, membungkam, dan menghilangkan sesuatu, tapi pada akhirnya malah membuat kesadaran terhadap hal tersebut justru bertambah.
Istilah ini terinspirasi dari kasus seorang penyanyi AS bernama Barbra Streisand yang menuntut foto rumah pribadinya di Malibu dihilangkan dari internet karena dianggap melanggar privasi, tuntutan tersebut akhirnya justru membuat semakin banyak orang tahu tentang kediamannya yang seharusnya menjadi rahasia.
Hal inilah yang terjadi pada kasus peretasan Narasi TV. Bukannya berhasil membuat kritik berhenti, oknum peretas ini justru sukses menarik perhatian luas publik terhadap “operasi intelijennya” untuk membungkam media. Alhasil, publik sekarang semakin berani berspekulasi bahwa memang sepertinya ada aktor-aktor kuat dengan kemampuan menyewa peretas yang ingin menjatuhkan kebebasan mengeluarkan pendapat.
Well, bisa kita simpulkan bahwa siapa pun yang jadi dalang di balik peretasan ini, maka sepertinya upaya pembungkamannya telah menjadi sebuah operasi intelijen yang blunder dan gagal. Tidak hanya itu, mereka juga sepertinya malah menciptakan efek hydra.
Layaknya seseorang yang ingin memenggal kepala makhluk mitologi Yunani bernama Hydra, yakni seekor ular dengan kemampuan regeneratif, setiap tebasan yang mereka lakukan justru malah memunculkan dua kepala ular yang baru.
Dalam konteks peretasan terhadap Narasi TV, “tebasan” yang dilakukan oknum peretas tersebut kepada media malah memunculkan masalah-masalah bercabang bagi mereka sendiri. Pertama, semakin banyak orang yang aware tentang upaya pembungkaman. Kedua, pihak yang ingin mereka “tebas” kini justru mendapat banyak dukungan – tidak hanya dari publik, tapi juga dari sejumlah lembaga advokasi dan aparat.
Pada akhirnya, kita perlu mengambil ini semua sebagai sebuah pembelajaran. Walau demokrasi memiliki kelemahannya tersendiri, tapi tetap saja, jika ada yang ingin mencederai kedaulatan rakyat, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan kemarahan rakyat itu sendiri sebagai timpalannya. (D74)



