Turunnya jumlah perempuan di legislatif pada Pileg 2014 dan rendahnya minat perempuan menjadi caleg di Pileg 2019, menimbulkan keprihatinan.
PinterPolitik.com
“Bagi saya, demokrasi yang lebih baik adalah demokrasi di mana perempuan tak hanya punya hak suara dan memilih, tapi juga hak untuk dipilih.” ~ Michelle Bachelet
[dropcap]S[/dropcap]ebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Presiden Chili (periode 2006-2010), Bachelet termasuk beruntung. Berbeda dengan Megawati Soekarnoputri yang “hanya” menjadi presiden setelah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilengserkan, Bachelet terpilih karena memang rakyat Chili sendiri yang menghendakinya.
Sebagai salah satu negara termakmur di Amerika Latin, sistem politik yang berlaku di Chili memang memberi porsi yang cukup besar bagi perempuan untuk berkiprah di dunia politik. Kabarnya, negara tersebut juga menerapkan aturan di mana calon legislatif laki-laki jumlahnya tidak boleh melebihi angka 60 persen.
Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan yang terjadi di Indonesia, walau undang-undang sudah menetapkan kuota anggota legislatif perempuan di angka 30 persen, namun hingga kini kuota tersebut tidak pernah tercukupi. Sebaliknya, jumlah perempuan di legislatif pada 2014 malah berkurang dibanding periode sebelumnya.
Saat advokasi UU Pemilu dlm rangka mperkuat afirmasi prempuan politik @perludem dkk mnuntut agr perempuan caleg ditempatkan di no. urut 1 pd paling sdikit 30% daerah pemilihan. Konsiderannya: krn tingkat kterpilihan caleg 80% lebih brada di no. urut 1 & 2. Tap advokasi ini gagal.
— Titi Anggraini (@titianggraini) March 7, 2018
Keprihatinan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, apalagi perempuan yang ikut pencalonan legislatif untuk bertarung di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, jumlahnya juga ikut turun dibandingkan pada tahun 2014.
Padahal, dalam data “Perempuan dalam Politik: 2017” yang dikeluarkan UN Women – lembaga PBB untuk permasalahan perempuan, Indonesia hanya berada di urutan 99 karena jumlah anggota legislatif perempuannya hanya sekitar 111 orang atau 19,8 persen. Posisi ini sedikit lebih rendah dari Arab Saudi yang berada di posisi 98 (19,9 persen).
Titi khawatir kalau jumlah keterwakilan perempuan di DPR akan semakin rendah setelah Pileg 2019, mengingat animo perempuan yang mendaftarkan diri sebagai caleg, hingga saat ini masih rendah. Ia menduga, para perempuan yang pernah mendaftar sebelumnya mengalami trauma dengan kompetisi yang ada.
Gender dan Rekayasa Masyarakat
“Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, tanyakanlah pada laki-laki. Tapi jika Anda ingin mengerjakan sesuatu, mintalah pada perempuan.” ~ Margaret Thatcher
Perdana Menteri (PM) Inggris dengan masa jabatan terlama sepanjang abad ke-20 (1979–1990) ini, dikenal sebagai “ si wanita besi” (the iron lady). Sebutan ini, ia dapatkan terkait dengan gaya kepemimpinan dan keputusan-keputusannya yang konservatif, sehingga banyak orang menyebut kebijakannya sebagai Thatcherisme.
Tak banyak yang tahu, kalau Thatcher memulai karir politiknya melalui legislatif. Namun saat Partai Konservatif mulai goyah, ia langsung mengambil kesempatan tersebut dengan mencalonkan diri sebagai calon pemimpin partai. Demi meraih kemenangan, ia pun mengubah penampilannya – baik cara berpakaian, gaya rambut, bahkan suaranya.
Dengan tampilannya yang lebih tegas dan melepaskan simbol-simbol feminin – seperti tidak lagi mengenakan topi, memotong pendek rambut, dan mengeraskan suaranya – pada Februari 1975, Thatcher akhirnya berhasil terpilih dan secara resmi menjabat sebagai Pemimpin Partai Konservatif.
Upaya Thatcher menjadi perempuan pertama yang memimpin partai politik, dengan melepaskan simbol feminin didirinya, dapat dikaitkan dengan upayanya untuk melakukan rekayasa sosial (social construction), untuk menghilangkan stereotype gender yang menurut Karl Marx dan Fredrich Engels memang sengaja dilakukan masyarakat.
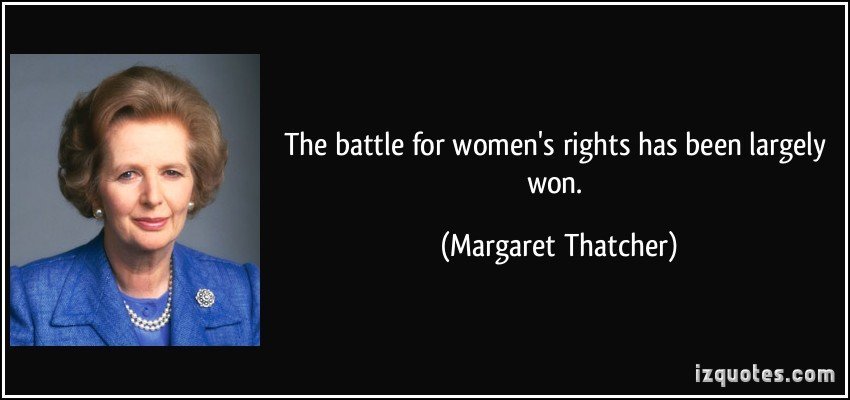
Dalam artikel berjudul “Neue Rheinische Zeitung politisch Ekononomische Revue” yang ditulis keduanya pada 1850, dijelaskan kalau masyarakat sengaja melakukan dualisme budaya untuk memisahkan laki-laki dan perempuan. Analisa mereka kemudian diperkuat oleh riset sosiologis yang dilakukan oleh Marcia Millman dan Rosabeth Moss Kanter.
Hasil penelitian yang dituang dalam makalah berjudul “Another Voice: Feminist Perspectives on Social Life and Social Science” ini, memperlihatkan kalau masyarakat memang sengaja membuat pembatasan bidang yang sifatnya konvensional, sehingga problema yang timbul sangat merugikan perempuan.
Padahal, bagi Marx dan Engels, posisi perempuan sebenarnya merupakan kunci dalam menentukan perkembangan masyarakat. Namun akibat adanya pembatasan tersebut, perempuan menjadi kelompok yang dibungkam (the muted group), karena bila kehendak dan pemikirannya tidak diterima masyarakat, ia akan dikucilkan.
Teori Pembungkaman Kelompok ini sendiri, dikemukakan oleh Shirley Ardener dalam bukunya “A First Look at Communication Theory”. Berdasarkan pengamatannya, pembungkaman ini pada akhirnya membuat perempuan tidak mampu dalam mengekspresikan dirinya secara lantang, di sektor-sektor yang didominasi laki-laki.
Kendala Perempuan dalam Politik
“Anda dapat mengatakan kalau saya tidak pernah merendahkan diri sendiri, tak ada yang salah dengan menjadi ambisius.” ~ Angela Merkel
Ambisi pula yang membawa Merkel menjadi the new iron lady, menggantikan Thatcher. Seperti juga PM Inggris tersebut, Merkel mampu menguasai Eropa dan memiliki masa kepemimpinan yang cukup panjang di negaranya. Baru-baru ini, melalui Pemilu yang demokratis, ia kembali terpilih sebagai Kanselir Jerman untuk keempat kalinya.
Saat ini, Merkel tak hanya memimpin negara, sebab perempuan protestan kelahiran Jerman Timur ini, juga menjadi Ketua Partai Demokrat Kristen (PDK) yang didominasi laki-laki asal Jerman Barat dan sebagian besar beragama katolik. Meski begitu, terbukti kalau Merkel tak hanya mampu mengubah mindset partainya, tapi juga rakyat Jerman.
Sebagai pemimpin partai politik pertama di Jerman, sudah tentu Merkel harus bersaing dengan banyak laki-laki dalam karir politiknya. Tak tanggung-tanggung, di bawah kendali Merkel, PDK yang awalnya bersifat tradisional kini malah menjadi salah satu pilar konsensus Jerman yang baru, termasuk membuat kuota perempuan di parlemen.
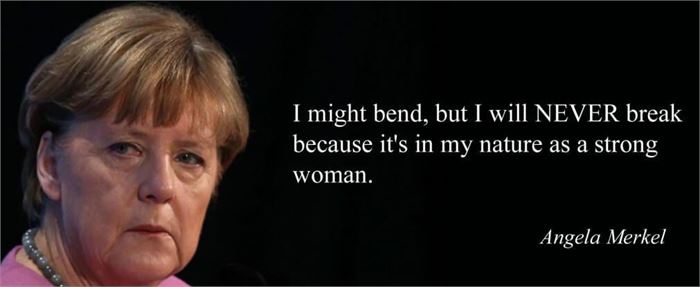
Bila ditilik dari teori kekuasaan menurut Robbins dan Judge, apa yang dilakukan Merkel memperlihatkan kemampuannya dalam mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga berperilaku atau berpikir seperti yang ia harapkan. Namun bagi seorang perempuan, terutama dalam lingkungan konservatif agamis, apa yang ia lakukan tentu tak mudah.
Di sisi lain, kemampuan Merkel ini juga dapat ditiru oleh para perempuan politisi di tanah air. Hanya saja, seperti yang disayangkan oleh Titi dari Perludem, sistem partai politik Indonesia masih penuh dengan politik transaksional. Inilah yang salah satunya menyebabkan perempuan sulit untuk bersaing dengan para politisi pria.
Walaupun keikutsertaan perempuan pada Pilkada tahun ini mengalami peningkatan, begitu juga dengan jumlah menteri perempuan di dalam kabinet, namun keterwakilan perempuan di legislatif jumlahnya masih memprihatinkan. Bahkan dapat dikatakan kecenderungannya terus menurun.
Menurut Titi, selain dari hambatan yang terjadi di internal parpol, faktor motivasi bagi perempuan untuk terjun ke politik pun masih sangat sedikit. Selain masih menganggap politik sebagai ranah pria, perempuan yang pernah ikut penjaringan legislatif pun umumnya trauma dengan persaingan atau kompetisi yang dianggap terlalu bebas.

Kompetisi yang sengit dan terkadang keluar dari rambu etika, umumnya harus dihadapi oleh para caleg tersebut sendirian. Padahal sebenarnya, bila saja Bawaslu dan KPU ikut mengawasi agar kompetisi yang terjadi tetap pada koridor standar yang ditetapkan, tentu akan membuat persaingan menjadi semakin dinamis (dynamic competition).
Oleh karena itu, Titi menawarkan tiga strategi bagi perempuan yang ingin menjadi caleg. Strategi pertama, ia harus mampu menguasai aturan main, target, dan prioritas kerja saat masuk ke dalam kompetisi. Juga termasuk memahami strategi komunikasi yang akan dipakai guna mendapatkan kemenangan.
Strategi selanjutnya, caleg harus membangun relasi dengan Bawaslu, sehingga terbangun ikatan mitra kerja yang baik. Terakhir, caleg juga harus membangun keterbukaan dan integritasnya di mata masyarakat. Bila itu semua dapat dilakukan, bisa jadi politik tidak akan terlihat “seram” lagi. Sederhananya, bila laki-laki bisa, mengapa perempuan tidak. (R24)




