Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat menggunakan teknologi A.I.
Indonesia sempat alami euforia sains dan imajinasi yang tinggi ketika awal hingga pertengahan Orde Baru. Mengapa tren tersebut tiba-tiba hilang?
Semua orang pasti mengenal dua raksasa dunia komik: Marvel dan DC. Kedua penerbit ini terkenal sebagai “pabrik” karakter pahlawan super dan ide-ide sains fiksi. Dalam beberapa tahun terakhir, eksistensi mereka semakin menonjol di berbagai media modern, mulai dari film hingga gim video.
Kesuksesan Marvel dan DC tentu tidak lepas dari imajinasi tinggi dan minat besar masyarakat Amerika Serikat terhadap ilmu pengetahuan. Amerika bisa dibilang sebagai rumah industri sains fiksi dan pahlawan super, di mana keberhasilan suatu industri sangat dipengaruhi oleh selera dan kebutuhan konsumennya.
Namun, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa di masa lalu, Indonesia pernah memiliki semangat serupa dalam industri pahlawan super dan sains fiksi. Pada era akhir Orde Lama hingga pertengahan Orde Baru, banyak komikus Indonesia yang menghasilkan karya populer, seperti Widodo Noor Slamet dengan karakter Godam dan Harya Suraminata dengan Gundala.
Menariknya, periode ini juga dikenal oleh sebagian orang sebagai “Era Keemasan Sains” di Indonesia, karena dibarengi dengan berdirinya institusi-institusi penting seperti LAPAN, LIPI, dan Dewan Penerbangan dan Antariksa Luar Republik Indonesia.
Karena itu, pantas juga untuk dispekulasikan bahwa emangat terhadap ilmu pengetahuan dan imajinasi yang tinggi tampaknya pernah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia pada masa itu. Namun anehnya, perlahan semangat ini memudar saat memasuki era reformasi.
Lantas, menarik untuk kita pertanyakan, apa yang menyebabkan tren ini hilang?

Keminatan & Imajinasi = Kemajuan Negara?
Kemajuan sains suatu negara tidak hanya diukur dari jumlah penemuan atau inovasi teknologinya, tetapi juga dari sejauh mana masyarakatnya memiliki ketertarikan terhadap produk budaya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mengonsumsi ilmu pengetahuan secara akademis, tetapi juga memahaminya melalui media populer.
Namun, di Indonesia, tren yang begitu positif akan ilmu pengetahuan dan “dunia imajinasi” perlahan-lahan menghilang menjelang akhir era Orde Baru. Dan entah berhubungan atau tidak, degradasi ini jika diamati cukup berjalan bersamaan dengan berkurangnya dukungan pemerintah ke program-program saintifik strategis.
Lembaga-lembaga sains di Indonesia pada masa itu sebenarnya memiliki potensi besar. LAPAN, misalnya, pernah menjadi ujung tombak dalam penelitian antariksa, sedangkan LIPI aktif dalam berbagai riset ilmiah. Namun, seiring berjalannya waktu, dukungan pemerintah terhadap lembaga-lembaga ini terus berkurang.
Hal ini terjadi setidaknya ketika periode tahun 1980-an, ketika terjadi pergeseran kebijakan pemerintah yang berdampak pada penurunan perhatian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
Fokus utama pemerintahan Presiden Soeharto saat itu adalah stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam. Akibatnya, sektor penelitian dan pengembangan (litbang) mengalami penurunan prioritas. Hal ini tercermin dari berkurangnya anggaran dan dukungan terhadap lembaga-lembaga penelitian seperti LIPI dan LAPAN.
Selain itu, menariknya, kurikulum pendidikan pada pertengahan hingga akhir masa Orde Baru pun lebih menekankan pada pembinaan ideologi negara dan pengetahuan dasar, dengan pendekatan yang otoriter dan birokratis, sehingga kurang mendorong kreativitas dan inovasi dalam bidang sains.
Lantas, seberapa mungkin semua hal ini merupakan suatu hal yang direkayasa?
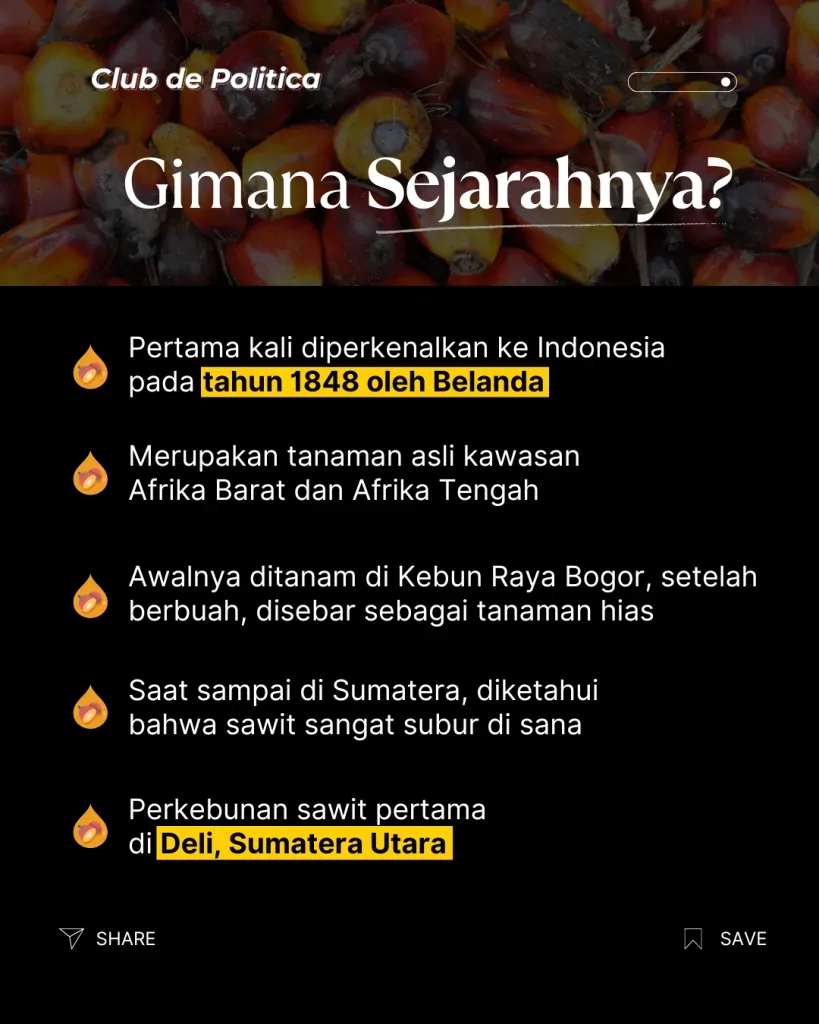
Mungkinkah Rekayasa Sosial?
Kemunduran minat terhadap sains dan pengurangan dukungan terhadap lembaga-lembaga penelitian di Indonesia pada akhir era Orde Baru bisa jadi bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari pola rekayasa sosial yang sering dilakukan oleh sejumlah otoritas yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu.
Rekayasa sosial pada dasarnya adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk memengaruhi pola pikir, perilaku, dan prioritas masyarakat. Di Amerika Serikat, misalnya, selama Perang Dingin, pemerintah secara aktif mempromosikan sains dan teknologi sebagai bagian dari “Perlombaan Antariksa” melawan Uni Soviet.
Melalui media, pendidikan, dan hiburan, masyarakat didorong untuk mengagumi ilmuwan dan menganggap sains sebagai simbol kekuatan nasional. Namun, pasca berakhirnya perlombaan tersebut, fokus pemerintah beralih, dan minat terhadap sains di kalangan publik secara perlahan menurun.
Kasus lain dapat dilihat di Uni Soviet, di mana pemerintah memprioritaskan teknologi dan inovasi yang mendukung militer dan ekonomi negara. Sektor-sektor yang tidak dianggap strategis sering kali ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat membentuk arah perkembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat.
Kembali ke Indonesia, pola serupa terlihat ketika fokus pemerintahan Orde Baru bergeser dari pengembangan ilmu pengetahuan menuju stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam. Dalam konteks ini, pengurangan dukungan terhadap lembaga-lembaga penelitian seperti LIPI dan LAPAN bisa jadi merupakan bagian dari strategi untuk mengalihkan perhatian masyarakat.
Jika benar ada rekayasa sosial dalam pengalihan fokus ini, hal tersebut tidak sepenuhnya mengejutkan. Sebagai alat kontrol sosial, rekayasa semacam ini sering kali digunakan oleh negara untuk menciptakan stabilitas atau memperkuat kekuasaan.
Bagaimanapun juga, tren ketersukaan terhadap sains dan daya imajinasi yang tinggi harus kita kembalikan semampu mungkin, karena hal ini mampu menjadi benih dari kemajuan iptek sebuah negara. Untuk saat ini, mungkin jawabannya ada pada upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung daya kritis, imajinasi, dan rasa ingin tahu, baik melalui pendidikan, media, maupun kebijakan yang berpihak pada pengembangan sains. (D74)



