Rivalitas perdagangan senjata antara dua kekuatan dunia, yakni Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok luput dari pembahasan para calon presiden (capres) 2024 dalam debat kemarin lusa. Padahal, itu agaknya sangat penting karena akan mempengaruhi strategi politik luar negeri Indonesia. Mengapa demikian?
Dalam debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hari Minggu (7/1), ketiga calon presiden (capres) tidak menyinggung tentang rivalitas yang meningkat antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, terutama terkait dengan perdagangan senjata.
Padahal, isu itu kiranya sangat strategis untuk dibahas dalam debat capres yang nantinya akan memberikan gambaran tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia jika terpilih menjadi presiden.
Pasalnya, baru-baru ini tensi rivalitas kedua negara kembali meningkat terkait dengan perdagangan alutsista. Penyebabnya adalah, Tiongkok menjatuhkan sanksi kepada lima produsen senjata asal AS karena menjual senjata kepada Taiwan.
Penjatuhan sanksi ini membuat kondisi makin panas, karena Beijing mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya.
Sementara itu, Washington memprotes sanksi itu dengan menyatakan negaranya diwajibkan oleh hukum untuk memberi Taiwan sarana untuk mempertahankan diri.
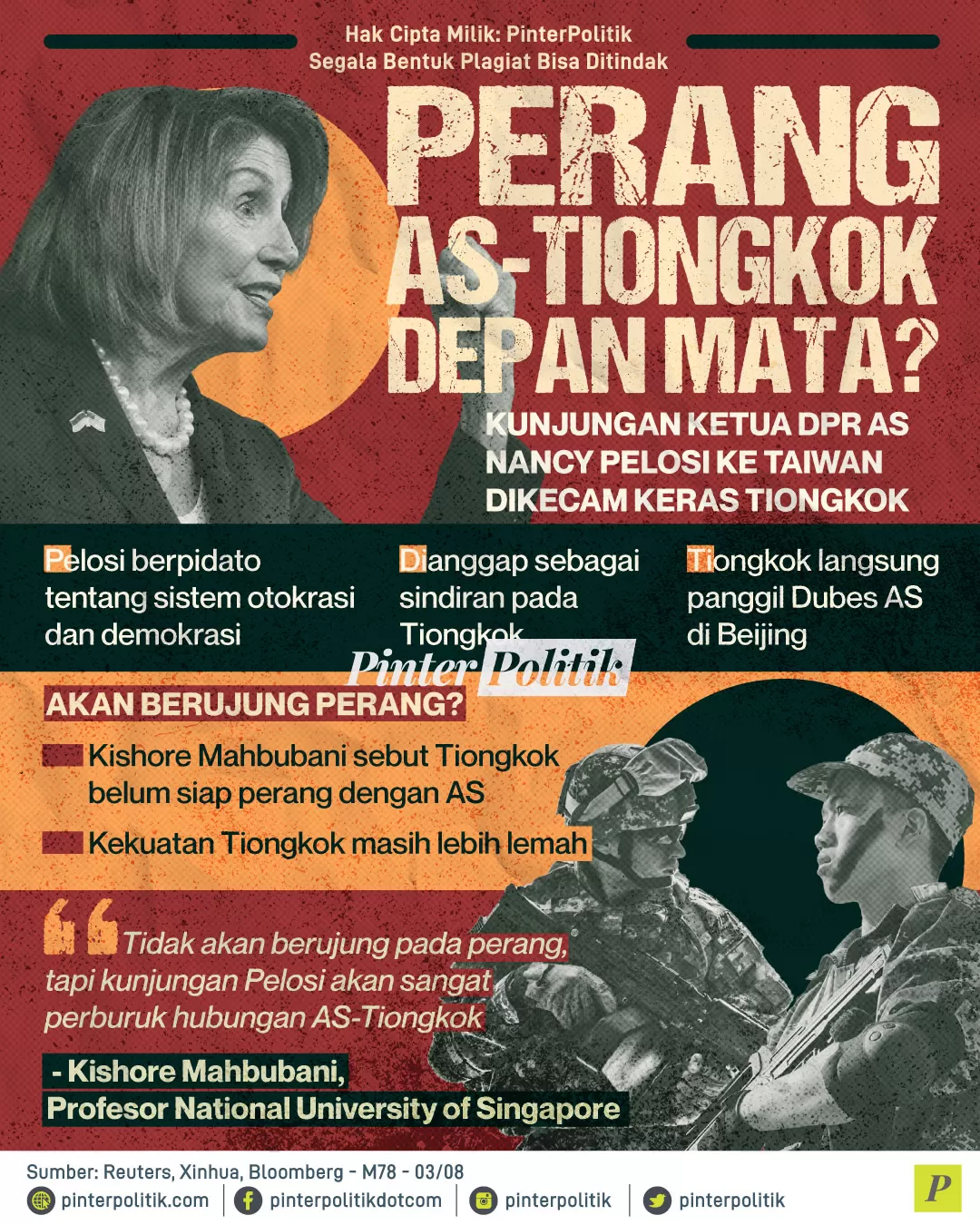
AS dan Tiongkok, sebagai dua kekuatan utama dalam arena geopolitik, secara rutin bersaing dalam penjualan senjata ke berbagai negara di dunia.
Negeri Paman Sam telah lama menjadi pemimpin dalam industri senjata global, dengan penjualan senjata yang luas dan teknologi yang canggih dengan proporsi pangsa pasar 40% secara global.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok juga meningkatkan eksportasi senjata mereka, menawarkan opsi yang lebih murah dan, dalam beberapa kasus, teknologi yang memadai.
Pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir ditambah dengan kampanye modernisasi militer yang berkelanjutan telah memungkinkan Tiongkok muncul sebagai pemain utama dalam perdagangan senjata global.
Sebelumnya, Beijing impor senjata konvensional mereka beberapa kali lebih banyak daripada yang dijual ke luar negeri. Namun, selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah berubah menjadi eksportir senjata.
Dari tahun 2010 hingga 2020, Tiongkok mengekspor hampir 16,6 miliar senjata konvensional senilai TIV (trend-indicator values) ke seluruh dunia.
Sekitar 77,3 persen jatuh ke Asia, 19,1 persen lagi mengalir ke Afrika, dan 3,6 persen sisanya mengalir ke belahan dunia lain.
Lantas, berdasarkan data diatas, mengapa perdagangan senjata menjadi sesuatu yang penting dibahas dalam debat?
Dibutuhkan Kebijaksanaan?
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki posisi geopolitik yang penting di kawasan Asia Tenggara.
Dalam menghadapi rivalitas AS-Tiongkok dalam perdagangan senjata, Indonesia berada dalam situasi yang rumit. Indonesia kiranya terus berusaha mempertahankan keseimbangan antara kemitraan ekonomi dan politik dengan AS dan Tiongkok.
John J. Mearsheimer dalam bukunya The Tragedy of Great Power Politics, situasi anarki dalam politik internasional membuat negara-negara berfokus menguatkan diri agar tidak merasa terancam.
Semakin insecure negara-negara tersebut, maka semakin banyak senjata dan kekuatan militer yang dibutuhkan. Solusinya pun adalah dengan menciptakan atau membeli senjata.
Meskipun Indonesia cenderung untuk memperoleh senjata dari berbagai sumber, peningkatan tekanan dari AS maupun Tiongkok bisa memaksa mereka untuk membuat komitmen yang lebih tegas terhadap salah satu pihak.
Indonesia kiranya harus mempertimbangkan arah kebijakan politik luar negeri agar tidak terseret ke dalam salah satu kubu, baik AS ataupun Tiongkok dan tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Brian Healy dan Arthur Stein dalam publikasinya yang berjudul The Balance of Power in International History: Theory and Reality memperkenalkan konsep triadic balance.
Konsep ini menjelaskan bahwa dalam sebuah dilema antara memilih dua kubu negara besar, suatu negara berkembang yang umumnya menjadi korban pertikaian.
Sehingga, negara berkembang itu membutuhkan adanya alternatif ketiga sebagai jalan keluar yang bisa menempatkan mereka sebagai negara yang netral dan turut memproyeksikan keseimbangan kekuatan (balance of power).
Di tengah rivalitas AS-Tiongkok dalam perdagangan senjata, Indonesia kiranya harus mempertimbangkan langkah-langkah bijaksana dalam strategi politik luar negerinya.
Perluasan kerja sama dalam bidang pertahanan dengan berbagai negara, kebijakan netralitas yang diperkuat, dan peningkatan kapasitas pertahanan domestik mungkin menjadi strategi yang diperlukan untuk menjaga kemerdekaan politik Indonesia dari tekanan eksternal.
Atas dasar itu, tampaknya sudah semestinya dalam debat capres kemarin para calon membahas persaingan dua kubu negara kuat, yakni AS dan Tiongkok agar para pemilih memiliki gambaran tentang arah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Mengapa demikian?

Senjata Bagian Diplomasi
Dengan eskalasi keamanan internasional yang meningkat belakangan ini terutama di kawasan Asia-Pasifik tampaknya membuat Indonesia membutuhkan peremajaan sistem persenjataan.
Namun, demi memenuhi hal itu dibutuhkan hubungan dengan negara lain yang juga merupakan negara produsen senjata. Terbaru, Indonesia membeli 42 jet tempur Rafale dari Perancis untuk memenuhi kebutuhan alutsista.
Andrew J Pierre dalam tulisannya yang berjudul Arms Sales: A New Diplomacy, mengatakan bahwa perdagangan senjata telah menjadi instrumen yang sangat prominen dalam konteks diplomasi.
Hal ini terjadi lantaran instrumen-instrumen konvensional seperti aliansi formal, penempatan pasukan di luar negeri, dan ancaman-ancaman intervensi langsung sudah tak terlalu efektif.
Diplomasi senjata merupakan bagian tak terpisahkan dari hubungan internasional di mana negara-negara menjalin kesepakatan terkait penjualan, pengadaan, dan penggunaan senjata di tingkat global.
Peran diplomasi senjata tidak hanya mencakup aspek perdagangan, tetapi juga memperhitungkan keamanan nasional, stabilitas regional, serta pengaruh politik dan ekonomi.
Penjualan senjata sering kali digunakan untuk memperkuat kemitraan strategis, memperoleh pengaruh politik, dan mempertahankan stabilitas regional.
Dengan disepakatinya pembelian jet tempur Rafale tampaknya buah dari keberhasilan Indonesia menghadirkan kepercayaan dari Perancis selaku negara produsen jet tempur Rafale untuk menjadi “partner strategis” bagi Indonesia.
Hal itu juga terlihat dari nominal kesepakatan antara Indonesia dan Perancis yang secara anggaran kiranya menguntungkan Indonesia.
Indonesia berhasil mendapatkan 42 unit jet tempur dengan harga Rp125,7 triliun, sedangkan India pada tahun 2016 lalu membeli 36 jet tempur Rafale dengan harga Rp136,6 triliun.
Rivalitas perdagangan senjata antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak hanya memiliki implikasi langsung bagi kedua negara tersebut, tetapi juga mempengaruhi strategi politik luar negeri negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Indonesia, dengan kedudukan strategisnya, dihadapkan pada tekanan untuk memilih di antara kedua kekuatan besar tersebut.
Namun, dengan mengedepankan diplomasi yang cermat, kerjasama multilateral yang kuat, dan kebijakan pertahanan yang bijaksana, Indonesia dapat menjaga independensinya dan kepentingan nasionalnya di tengah rivalitas global yang sedang berlangsung.
Seperti pembelian jet tempur Rafale yang tampaknya bertujuan untuk menjaga kedudukan strategisnya dicantara rivalitas AS dan Tiongkok.
Namun, sayangnya hal-hal seperti yang diungkapkan diatas luput dari pembahasan debat ketiga Pilpres 2024 yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. (S83)



