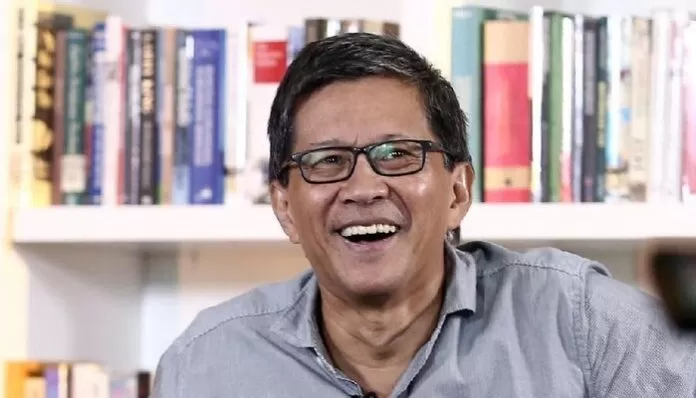Mengomentari kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini, Rocky Gerung menyarankan agar gedung Kejagung tidak perlu direnovasi karena dapat menjadi monumen buruknya pemberantasan korupsi. Pertanyaannya, jika nantinya saran Rocky diikuti, mungkinkah pendapatnya akan teraktualisasi?
“Monuments are the grappling-irons that bind one generation to another” – Joseph Joubert
Dengan statusnya sebagai salah satu gedung vital, kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini telah menyita perhatian publik. Berbagai narasi juga muncul sebagai respons atasnya. Menariknya, tidak sedikit yang menyebutkan terdapat upaya sabotase atau penghilangan jejak perkara, menimbang pada terdapat berbagai kasus besar seperti Jiwasraya dan Djoko Tjandra yang kini tengah ditangani Kejagung.
Di samping perdebatan mengenai apakah gedung Kejagung dibakar atau tidak, narasi yang mencuat juga perihal renovasi gedung vital tersebut. Karena diperkirakan belum diasuransikan, biaya renovasi gedung diperkirakan menyentuh angka Rp 161 miliar.
Uniknya, dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada 25 Agustus, pengamat politik Rocky Gerung justru menyarankan agar renovasi tersebut tidak dilakukan. Menurutnya, gedung yang terkabar tersebut dapat menjadi monumen untuk mengingatkan publik tentang buruknya pemberantasan korupsi dan terbakarnya keadilan.
Ya, meskipun terdengar seperti pernyataan satire semata, saran dari Rocky sebenarnya menyimpan dimensi kebenaran tersendiri. Monumen sendiri memang menjadi pengikat ingatan publik dan sejarah. Monumen patung Jenderal Sudirman misalnya, ini mengingatkan publik terhadap jasa besar sang jenderal.
Tentu sekarang pertanyaannya, jika satire Rocky ini katakanlah benar-benar dilakukan, mungkinkah dibiarkannya gedung Kejagung yang terbakar dapat menjadi monumen seperti yang disebutkannya?
Monumen sebagai Memori Kolektif
Marija Kulišić dan Miroslav Tuđman dalam tulisannya Monument as a Form of Collective Memory and Public Knowledge menyebutkan bahwa monumen dapat berperan sebagai memori kolektif dan pengetahuan publik dalam masyarakat kontemporer. Mengutip penulis dan seniman asal Prancis, Quatremère de Quincy, monumen didefinisikan sebagai tanda yang membangkitkan peristiwa, objek, ataupun individu tertentu.
Memori kolektif sendiri adalah fenomena yang dibangun melalui komunikasi, yang kemudian menjadi bagian dari kelompok yang berpartisipasi karena mengonstruksi identitas dan cenderung mengkristal, sehingga rekonstruksi masa lalu akan menjadi bagian dari masa kini dan masa depan.
Tidak hanya terjadi di masyarakat kontemporer, penggunaan monumen sebagai memori kolektif, nyatanya sudah ditemukan sejak kebudayaan Yunani dan Mesir Kuno. Mengutip egyptologist kontemporer, J. Assman, masyarakat Mesir Kuno telah lama menjadikan kuil untuk menghadirkan memori masa lalu dan dunia yang kekal di masa depan.
Saat ini, kita melihat bagaimana piramida-piramida di Mesir tidak hanya menjadi objek wisata, melainkan juga sebagai pengingat besarnya kebudayaan Mesir Kuno. Ini juga turut menjadi medium untuk melimpahkan kebanggaan pemerintah Mesir saat ini.
Akan tetapi, Kulišić dan Tuđman menegaskan bahwa memori kolektif tidak dapat terbentuk begitu saja. Persoalan ini misalnya dapat kita lihat dengan berbagai bangunan bersejarah ataupun karya-karya kuno yang tergeletak begitu saja tanpa mendapatkan perhatian berarti dari masyarakat kontemporer. Lagi pula, seperti yang disebutkan oleh penulis asal Inggris, J. Ruskin, manusia merupakan individu yang mudah melupakan sesuatu.
Untuk menjadikan suatu tanda menjadi memori kolektif diperlukan komunikasi intensif dari masa ke masa untuk membuatnya tetap dikenang oleh masyarakat. Ini yang membuat Kulišić dan Tuđman menyebut monumen sebagai bentuk dari objek komunikasi.
Piramida Mesir misalnya, ini menjadi memori kolektif masyarakat Mesir, bahkan dunia, karena terus dikomunikasikan secara intens melalui berbagai medium pemberitaan. Mulai dari buku sejarah, iklan televisi dan elektronik, hingga dijadikan objek penelitian para ilmuwan. Ini membuat Piramida sebagai memori kolektif tetap bertransmisi dari generasi ke generasi.
Dalam kesimpulannya, Kulišić dan Tuđman menyebut monumen tidak dapat dipahami sebagai tanda pasif, melainkan sebagai tanda aktif, karena monumen membutuhkan interaksi komunikasi aktif dalam kegiatan sosial. Kembali mengutip Ruskin, nilai monumen terletak pada kemampuannya untuk bersaksi secara terus menerus tentang orang-orang ataupun perjalanan waktu, dengan tujuan menghubungkan masa-masa yang terlupakan dengan yang akan datang.
Setelah memahami bagaimana suatu tanda dapat menjadi monumen, sekarang patut untuk dipertanyakan, apabila nantinya gedung Kejagung tidak direnovasi seperti dalam usulan Rocky, mungkinkah gedung ini menjadi monumen?
Belum Tentu Terwujud?
Seperti dalam penjelasan Kulišić dan Tuđman, suatu tanda atau objek tidak dapat begitu saja menjadi monumen, melainkan membutuhkan komunikasi intens yang membuatnya bertransmisi dari masa ke masa.
Konteks transmisi intens ini menjelaskan mengapa sosok seperti Munir, Marsinah, Wiji Thukul, hingga Novel Baswedan dapat menjadi memori kolektif dan pengetahuan publik akan buruknya penegakan HAM dan pemberantasan korupsi. Pasalnya, kasus-kasus tersebut hampir setiap hari diproduksi ulang di tengah masyarakat.
Aksi Kamisan misalnya, dengan ciri khas menggunakan pakaian serba hitam, narasi HAM dengan membawa foto sosok-sosok tersebut telah membuat ingatan publik tentang mereka seolah menjadi kekal dan terus bertransmisi dari masa ke masa. Padahal, berbeda dengan kasus Novel yang belum 5 tahun terjadi, kasus Munir, Marsinah, dan Wiji Thukul dapat dikatakan terjadi di generasi yang berbeda.
Aktivis muda saat ini tentu bukanlah saksi sejarah yang melihat perjalanan langsung kasus mereka. Namun, karena terus dikomunikasikan, kasus-kasus tersebut telah bertransmisi dan membentuk memori kolektif.
Sekarang pertanyaannya, mungkinkah gedung Kejagung dapat menjadi memori kolektif seperti dalam pernyataan Rocky?
Melihat sejarahnya, ini bukanlah kali pertama gedung tersebut terbakar. Pada hari Rabu, 10 Januari 1979 dan hari Minggu, 23 November 2003, gedung Kejagung juga pernah terbakar. Uniknya, penyelidikan menyebutkan bahwa kedua kebakaran tersebut disebabkan oleh korsleting listrik.
Tidak hanya pernah kebakaran, pada hari Selasa, 4 Juli 2000, bom bahkan pernah meledak di Gedung Bundar Kejagung. Menariknya, peristiwa tersebut terjadi berselang sekitar satu jam setelah Hutomo Mandala Putera atau Tommy Soeharto meninggalkan Kejagung, usai diperiksa sebagai saksi atas kasus sang ayah, Soeharto. Tidak hanya kasus Soeharto, saat itu Kejagung juga tengah serius menuntaskan kasus KKN, sehingga tidak sedikit yang menyebutkan ledakan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tengah tertekan.
Sekarang pertanyaannya, dengan berbagai deretan kasus tersebut, mengapa gedung Kejagung tidak menjadi monumen? Jawabannya kemungkinan besar karena peristiwa-peristiwa tersebut tidak secara intens dikomunikasikan dari masa ke masa, sehingga tidak bertransmisi.
Bertolak atas hal tersebut, sekarang pertanyaannya, seberapa intens sekiranya peristiwa kebakaran gedung Kejagung saat ini diberitakan ataupun dibahas? Jika tidak terdapat syarat komunikasi tersebut, besar kemungkinan kebakaran gedung Kejagung kali ini hanya akan menjadi angin lalu, seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya.
Artinya, sekalipun secara teoretis pernyataan Rocky dapat terafirmasi bahwa gedung Kejagung dapat menjadi monumen. Akan tetapi, persoalannya terletak pada komitmen berbagai pihak untuk memproduksi ingatan peristiwa ini melalui komunikasi yang intens.
Pada akhirnya, di luar perdebatan apakah gedung Kejagung kebakaran atau dibakar, tentu kita berharap agar kasus serupa tidak berulang lagi di kemudian hari. Saat ini kita masih menunggu hasil penyelidikan pihak berwenang untuk menentukan penyebab kebakaran yang telah terjadi.
Terkait peristiwa ini dapat membuat gedung Kejagung menjadi monumen atau tidak, hanya waktu yang dapat menjawabnya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)