Saat ini, DPR bersama Mendagri tengah mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Langsung. Mahfud MD bilang, Pilkada langsung banyak mudarat-nya. Benarkah?
PinterPolitik.com
“Kita bukan bodoh, tapi dibodohkan. Kita tidak miskin, tapi dimiskinkan. Oleh sebuah sistem.” ~ Ir. Soekarno
[dropcap]W[/dropcap]acana untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung kembali bergulir. Selain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Ketua DPR Bambang Soesatyo, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pun ikut menyetujuinya. Ketiganya menilai, pelaksanaan Pilkada Langsung yang saat ini dilakukan tidak berjalan efektif.
Pemikiran untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan Pilkada langsung ini, berawal dari pernyataan Tjahjo yang mengatakan biaya pelaksanaan Pilkada di beberapa provinsi yang totalnya mencapai Rp 18 triliun, sangat membebani Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Biaya tersebut belum termasuk yang dikeluarkan oleh partai politik maupun kandidat calon kepala daerah.
Mengembalikan kekuasaan pemilihan kepala suatu daerah ke tangan DPRD, bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sistem pemilihan umum langsung kepala daerah yang baru beberapa tahun dinikmati masyarakat, hampir saja direnggut dan dikembalikan kekuasaannya ke tangan legislatif.
Usulan yang datang dari Partai Golkar itu bahkan telah disahkan dalam UU No. 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD. Namun reaksi keras dari masyarakat akhirnya “memaksa” SBY menerbitkan tiga Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) sekaligus, guna mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan rakyat.

Belum genap empat tahun, usulan itu kembali digaungkan oleh Mendagri dan juga DPR. Selain biaya pelaksanaan yang tinggi, Mendagri pun mendapatkan alasan lain untuk memberangus pesta demokrasi dari tangan rakyat. Maraknya kepala daerah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, disinyalir merupakan konsekuensi dari biaya Pemilu yang harus ditanggung oleh partai politik dan para kandidatnya.
Kini Pemerintah bersama DPR kembali mengevaluasi kemungkinan “dihidupkan” UU N0. 22 tersebut. Apalagi, wacana ini juga didukung pakar hukum tata negara Mahfud MD yang menganggap Pilkada Langsung menimbulkan banyak kecurangan dan politik uang. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan Pilkada Langsung begitu mahal dan tidak efektif?
Dependensi Politik Tanah Air
“Kebaikan buat masyarakat itu bergantung kepada watak masyarakat, dan didikan masing-masing orang.” ~ Tan Malaka
Seperti yang juga dikemukakan oleh Tan Malaka di atas, bagi Mahfud, sistem Pilkada Langsung yang tidak memberikan manfaat dan malah jadi mudarat (merugikan), bisa jadi memang demi kebaikan masyarakat sendiri. Terutama karena selama ini, masyarakat masih belum mendapatkan pendidikan politik yang cukup untuk dapat menentukan pemimpinnya secara mandiri, tanpa adanya intervensi pihak lain.
Walau reformasi telah berjalan 20 tahun, namun buah pendidikan politik yang menerapkan sistem sentralisasi dan birokratisasi di masa Orde Baru, masih sangat kental di masyarakat. Selama 32 tahun, Soeharto telah berhasil menerapkan doktrin kepatuhan yang sangat kuat dalam masyarakat. Akibatnya, rakyat kehilangan daya kritis, daya kreatif, dan inovatifnya.
Intervensi yang besar terlihat dari aspek pendidikan kala itu, di mana muatan kurikulumnya dimanfaatkan pemerintah untuk tujuan melanggengkan kekuasaan. Indoktrinasi penguasa dibentuk tak hanya dari penyeragaman ideologi saja, tapi juga budaya, dan kearifan lokal lainnya. Bahkan, istilah Bhineka Tunggal Ika yang bermakna “berbeda-beda tapi tetap satu” diselewengkan menjadi bentuk entitas keseragaman.
Apa yang dilakukan Soeharto, sebenarnya sangat sejalan dengan Teori Ketergantungan (dependency theory) yang dikemukakan oleh Theotonio Dos Santos. Teori yang kerap digunakan dalam konteks ekonomi dan hubungan internasional ini, menyatakan kalau sejumlah negara inti memang sengaja mengeksploitasi beberapa negara yang lebih lemah demi kemakmuran mereka.
Meski di masa kepemimpinannya, Soeharto melarang dan menabukan ajaran Marxisme, namun sistem sentralistik yang dijalankannya sebenarnya seiring dengan teori dependensi yang terkait dengan ajaran Marxisme. Soeharto sengaja menempatkan DKI Jakarta – sebagai inti negara, posisinya dibuat lebih kuat melalui eksploitasi wilayah lain yang sengaja dilemahkan, agar terus bergantung pada pusat.

Ketergantungan ini, tak hanya berlaku pada pemerintahan, tapi juga pada pendidikan politik masyarakat. Di masa Orba, sebagai kendaraan politik Soeharto, Golkar menjadi partai pemerintah satu-satunya dan mampu mengintervensi pemilih hingga ke ranah privat, seperti ancaman PHK bagi karyawan atau dikeluarkan dari sekolah bila tidak memilih Golkar saat Pemilu.
Ketika era reformasi bergulir, sistem politik tanah air memasuki era baru seiring berubahnya sistem pemilihan umum. Namun sayangnya, perubahan sistem politik ini tidak diiringi pula dengan perubahan pola pandang politik masyarakat. Rendahnya pendidikan politik, pada akhirnya menjadi ujung pangkal Pilkada Langsung tidak efektif.
Antara Mudarat dan Manfaat
“Manusia dilahirkan bebas, tetapi di mana-mana mendapatkan dirinya terbelenggu.” ~ J.J. Rousseau
Pendidikan politik, menurut Pakar Ilmu Sosial dan Politik Kuswoyo Trihatmodjo, merupakan kunci dari keberhasilan Pilkada. Menurutnya, jika pendidikan politik masyarakat sebagai pemilih masih rendah, maka akan sangat mungkin menghasilkan pemimpin yang salah. Agar kondisi ini tidak terjadi, Kuswoyo berharap Pemerintah lebih menitikberatkan pada kesadaran politik masyarakat, terutama mengenai partisipasi politiknya.
Bila ditinjau dari Teori Partisipasi, saat ini masyarakat lebih cenderung menggunakan partisipasi mobilisasi akibat tingkat pendidikan dan kesejahteraannya masih relatif rendah. Menurut Huntington dan Nelson dalam buku “Partisipasi Politik di Negara-Negara Berkembang”, partisipasi mobilisasi ini merujuk pada adanya pengaruh pihak lain dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilih secara mandiri (partisipasi otonom).
Partisipasi mobilisasi ini sendiri, terbukti banyak digunakan para politisi di daerah-daerah dalam meraih kekuasaan. Faktanya terlihat dari bagaimana faktor kultural dan ketokohan, masih menjadi kriteria yang kuat bagi masyarakat saat memilih pemimpin. Di sisi lain, masyarakat juga sangat mudah dimobilisasi menggunakan isu-isu SARA, iming-iming uang, maupun kecurangan.

Kriteria masyarakat yang memilih bukan dari kemampuan calon pemimpin inilah, di mata Mahfud dianggap sebagai mudarat. Sebab pemimpin yang terlahir dengan menggunakan politik uang, pada akhirnya akan menjadi pemimpin korup karena hanya akan menggunakan jabatannya untuk “mengembalikan modal” yang telah terpakai saat memobilisasi pemilih.
Menghilangkan kemudaratan dengan mengembalikan hak memilih rakyat ke tangan parlemen, mungkin memang jalan termudah dan termurah bagi Pemerintah saat ini. Mahfud sendiri mengatakan kalau lebih mudah mengawasi anggota DPRD daripada mengawasi seluruh rakyat. Namun apakah jalan ini juga menjadi yang terbaik bagi masyarakat? Atau hanya keputusan pragmatis pihak-pihak yang punya kepentingan?
Sebagai pakar hukum, Mahfud tentu memahami Teori Kontrak Sosial (social contract theory) yang disampaikan Jean Jacques Rousseau maupun Thomas Hobbes. Keduanya sepakat bahwa dalam bernegara, rakyat memiliki ikatan kontrak untuk mewakilkan kekuasaan negara pada pihak tertentu demi kepentingan bersama. Pertanyaannya, Mahfud lebih cenderung menggunakan kontrak sosial ala Rousseau atau Hobbes?
Persetujuan Mahfud untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan Parlemen, cenderung setuju pada pandangan kontrak sosial menurut Hobbes. Filsuf beraliran empirisme ini berpendapat bahwa setelah negara terbentuk, maka kekuasaan negara tidak terikat lagi dengan individu (rakyat), sehingga dapat menentukan keputusan negara tanpa melibatkan rakyat.
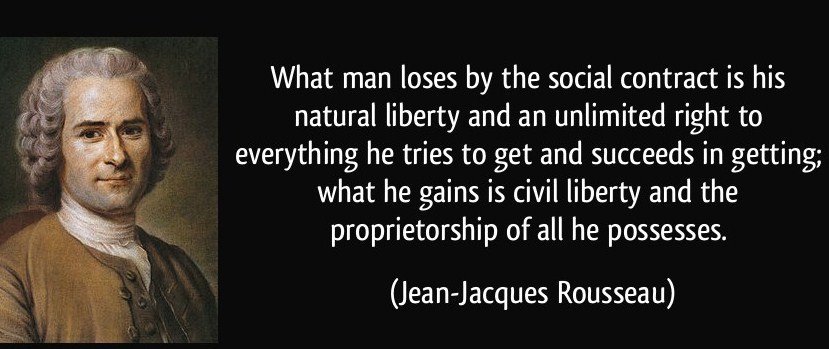
Dengan kata lain, saat rakyat setuju memberikan keterwakilannya pada anggota DPRD, maka DPRD dapat memutuskan siapa pemimpin suatu wilayah, tanpa persetujuan rakyat. Sistem Pilkada melalui DPRD ini, memungkinkan parpol memiliki suara sama. Hanya saja, apa Mahfud mampu menjamin kalau pemimpin yang dipilih DPRD akan lebih bersih dan terhindar dari intervensi kepentingan parpol?
Sementara sistem Pilkada Langsung yang dilakukan saat ini, sebenarnya adalah kontrak sosial paling ideal menurut Rousseau. Filsuf Prancis ini berkeyakinan kalau negara merupakan representasi kepentingan individu-individu di dalamnya. Sehingga rakyatlah yang menentukan sendiri penguasa dan pemimpinnya secara langsung, termasuk mandat untuk melengserkannya apabila dianggap gagal.
Bagi Rousseau, demokrasi langsung sangat ideal karena merupakan praktik demokrasi murni. Jadi kalau begitu, mengapa Mahfud malah berupaya mengubah sistem yang ideal dengan sistem yang hanya akan melanggengkan kekuasaan elit politik? Apakah alasan ongkos politik yang mahal dan pemimpin korup itu semata-mata kesalahan rakyat yang kurang memahami politik?
Bukankah kurangnya pendidikan politik masyarakat juga membuktikan kegagalan Pemerintah? Atau jangan-jangan, para elit memang sengaja mempertahankan kebodohan politik masyarakat layaknya ucapan Tan Malaka, “Politik pemerintah ini dalam soal pengajaran boleh disimpulkan, bangsa Indonesia harus tetap bodoh supaya ketentraman dan keamanan umum tetap terpelihara”.
Bila benar begitu, maka perkataan Bung Karno kalau kita dibodohkan oleh sistem, adalah suatu ironi. (R24)



