Status tanpa kewarganegaraan Rohingya dapat berujung pada hilangnya hak asasi manusia dan jaminan terhadap perlindungan hukum. Hal itu dapat berdampak bagi korban kekerasan seksual dimana perempuan menjadi senjata genosida. Mengapa demikian?
Berawal dari kudeta militer Myanmar yang terjadi pada 1962 hingga terbitnya undang-undang tahun 1982 yang telah melucuti status Rohingya sebagai kelompok etnis minoritas yang diakui, persoalan hak asasi manusia Rohingya seakan tak kunjung menemui titik terang yang berarti.
Banyak pengungsi Rohingya berusaha menyelamatkan diri dengan mengungsi ke negara-negara seperti Bangladesh, Indonesia, dan Malaysia. Pada tahun ini, Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) menyebutkan sekitar 2.400 orang Rohingya yang mengungsi di Bangladesh melakukan percobaan melarikan diri menuju Indonesia dan Malaysia.
Aksi itu dinilai sangat mengkhawatirkan lantaran dapat menjadikan tahun 2022 sebagai salah satu tahun yang paling mematikan di laut selama hampir satu dekade ke belakang. Para pengungsi rela melarikan diri karena merasa putus asa berada di kamp Bangladesh.
Selain itu, eksodus tersebut kemungkinan juga dipengaruhi oleh pencabutan kebijakan pembatasan alias lockdown Covid-19 di sekitar wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, faktor tersebut dapat menjadi keleluasaan para pengungsi untuk pindah negara.
Pernyataan anggota keluarga dan UNHCR menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 160 orang yang masih terdampar di lepas pantai India dengan kondisi kelaparan. Orang-orang itu bukan hanya terdiri dari orang dewasa, melainkan juga anak-anak dan perempuan.
Selain itu, pengungsi yang kabur dari kamp pengungsian Bangladesh juga berpotensi menjadi target perdagangan manusia. Artikel dengan judul Rohingya Women, Girls Being Trafficked to Malaysia for Marriage yang ditulis oleh Kaamil Ahmed pada tahun 2019 lalu menyatakan beberapa perempuan diperdagangkan, termasuk di antaranya keluarga Rohingya yang tersisa di Myanmar dan harus memasuki Bangladesh hanya untuk masuk kembali ke wilayah yang kurang termiliterisasi.
Lantas, bagaimana akar permasalahan Rohingya yang seakan tidak memiliki hak asasi manusia mempermudah manusia untuk diperdagangkan, terutama kaum perempuan?

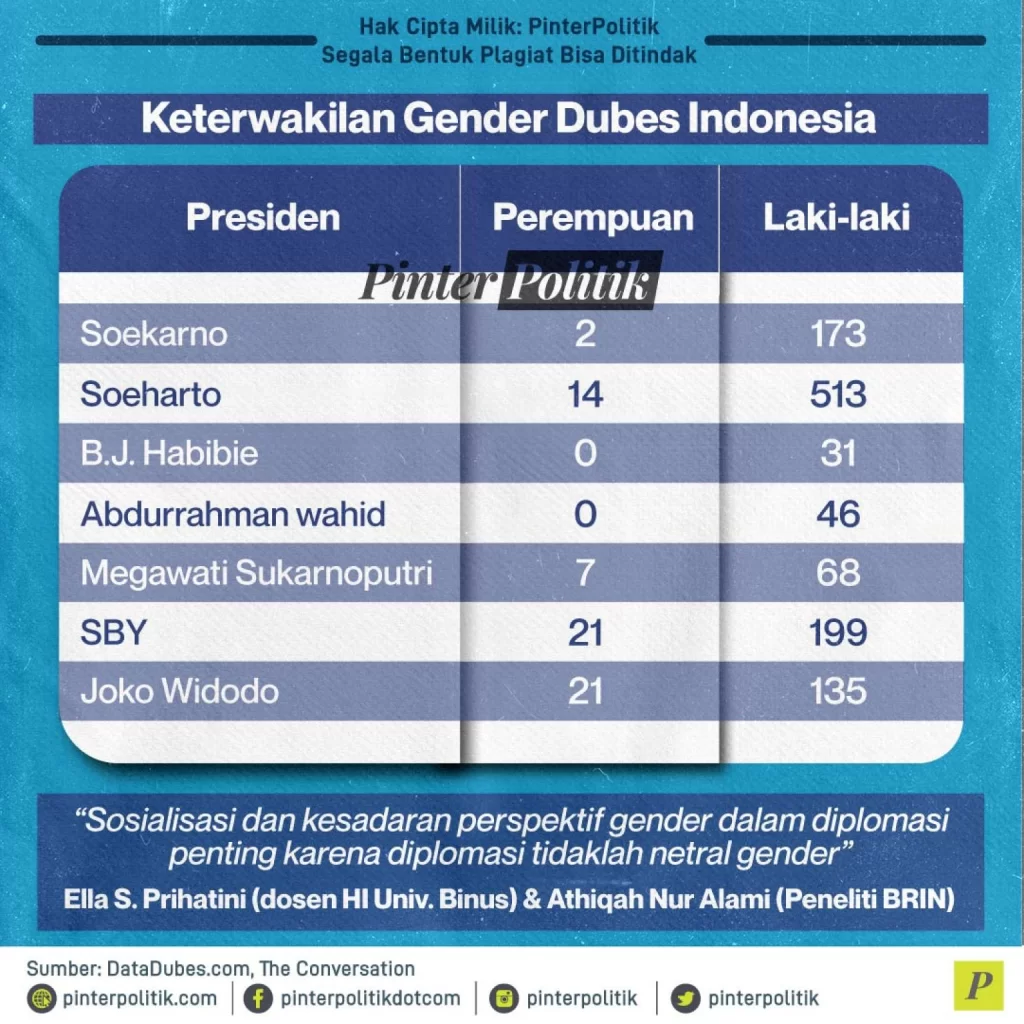
Etnis Tanpa Kewarganegaraan?
Penyebab utama mengapa persoalan hak asasi manusia etnis Rohingya selalu menjadi permasalahan yang pelik dipengaruhi oleh status mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan.
Menurut hukum internasional UNHCR, status tanpa kewarganegaraan diartikan sebagai seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan pelaksanaan hukumnya.
Artinya, orang tanpa kewarganegaraan tidak memiliki kewarganegaraan dari negara manapun baik karena terlahir tanpa kewarganegaraan maupun menjadi tanpa pengakuan kewarganegaraan melalui keturunannya.
Keadaan tanpa kewarganegaraan dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk diskriminasi terhadap kelompok etnis atau agama tertentu, jenis kelamin, munculnya negara-negara baru dan pengalihan wilayah, serta adanya kesenjangan dalam hukum kewarganegaraan.
Keadaan tanpa kewarganegaraan dapat memiliki akibat yang serius di hampir setiap negara dan di semua wilayah di dunia. Orang tanpa kewarganegaraan dapat mengalami kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Pada akhirnya, mereka dapat menghadapi rintangan dan kekecewaan seumur hidup.
Hal itu selaras dengan realita yang dihadapi orang-orang Rohingya. Hampir satu juta Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dan saat ini hidup dalam kondisi yang sangat genting di dekat perbatasan Myanmar-Bangladesh.
Kondisi ini diperparah dengan penindasan kejam terhadap tindakan kekerasan seksual yang dialami perempuan Rohingya selama beberapa dekade.
Suatu publikasi berjudul Gender-Based Violence in a Complex Humanitarian Context: Unpacking the Human Sufferings Among Stateless Rohingya Women yang ditulis oleh Grace Priddy, Zoe Doman, Emily Berry, dan Saleh Ahmed, mengemukakan kondisi perempuan Rohingya turut menyoroti kesehatan dan kesejahteraan.
Dan lebih mirisnya, kekerasan seksual terhadap gender bahkan menjadi salah satu strategi militer untuk melancarkan aksi genosida. Mengapa bisa demikian?

Perempuan, Senjata Genosida?
Menurut publikasi Sexual violence against women as a weapon of Rohingya genocide in Myanmar yang ditulis oleh Afroza Anwary kekerasan seksual merupakan salah satu strategi, praktik, dan proses dalam upaya genosida terhadap etnis Rohingya.
Sebelumnya, peristiwa pembunuhan massal terhadap Rohingya terjadi pada bulan Juni dan Oktober 2012. Peristiwa itu menyusul desas-desus bahwa seorang wanita Buddha Rakhine diperkosa dan dibunuh oleh pria Rohingya.
Kabar tersebut kemudian menyulut militer untuk bertindak keras disusul dengan kerusuhan berikutnya yang membuat sebanyak 140.000 orang mengungsi.
Gelombang pembunuhan massal berikutnya terjadi setelah sensus pada 2014 ketika pemerintah memutuskan bahwa Rohingya hanya dapat mendaftar sebagai orang Bengali dan bukan sebagai Rohingya. Artinya, pemerintah menolak status kelompok etnis asli mereka.
Pemerkosaan massal terhadap perempuan Rohingya berlanjut hingga tahun 2017 dimana terdapat peningkatan kekerasan terhadap Rohingya setelah Arakan Rohingya Salvation Army membunuh dua belas pasukan keamanan perbatasan Myanmar-Bangladesh.
Pembunuhan tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk secara paksa mengirim Rohingya ke kamp-kamp interniran di mana hak asasi manusia Rohingya dicabut dan mengakibatkan lebih dari setengah juta Rohingya dipaksa keluar dari Myanmar oleh militer dan pasukan keamanan antara 25 Agustus dan 13 Oktober.
Mengacu pada meluasnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, pada awal tahun 2017 semua penyintas kekerasan berbasis gender menyebutkan bahwa tindakan kekerasan militer Myanmar telah secara brutal merugikan semua perempuan dan anak perempuan Rohingya.
Bahkan, menurut hasil wawancara dengan empat puluh pengungsi perempuan pengungsi Rohingya berusia 18 tahun yang tinggal di tempat penampungan Bangladesh menyatakan mereka kehilangan setidaknya satu anggota keluarga dekat dan/atau tetangga mereka selama genosida.
Dua belas responden menyebutkan bahwa mereka atau anggota keluarga dekat mereka atau penduduk desa lainnya menjadi korban kekerasan seksual dalam konflik oleh militer dan/atau pasukan keamanan Myanmar.
Selain itu, dua puluh responden menyebutkan bahwa mereka menyaksikan tetangga dan penduduk desa mereka menjadi korban oleh aparat keamanan.
Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan akses untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mampu memengaruhi keyakinan para pengungsi Rohingya bahwa nasib mereka dapat berubah jika menikah dengan warga negara tujuan pengungsian mereka, misalnya saja seperti Malaysia.
Perempuan dan anak bahkan rela untuk menikah dengan laki-laki yang bahkan belum mereka kenal di negara lain.
Realita tersebut lantas memperkuat pernyataan bahwa perempuan dapat menjadi senjata untuk melakukan genosida. Lantas, dukungan seperti apa yang dibutuhkan korban kekerasan seksual Rohingya?

Suarakan Kemanusiaan?
Sebelum masuk kepada jawaban pertanyaan di atas, penting untuk kita refleksikan pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres yang menyatakan bahwa kekerasan seksual sebagai bentuk perang fisik dan psikologis yang brutal yang berakar pada ketidaksetaraan gender terjadi tidak hanya di zona konflik, namun juga dalam kehidupan sehari-hari.
Kekerasan seksual juga dapat ditemukan di kamp pengungsian. Penelitian berjudul Situation of Sexual and Gender-Based Violence Among The Rohingya Migrants Residing in Bangladesh yang diteliti oleh Farzana Islam, Mohiuddin Hussain Khan, Masako Ueda, NM Robiul Awal Chowdhury, Salim Mahmud Chowdhury, Mshauri David Delem, dan Aminur Rahman melaporkan bahwa kekerasan seksual umumnya terjadi dalam rumah tangga.
Mereka menambahkan bahwa selalu ada “ketegangan” antara Rohingya dan komunitas tuan rumah. Adapun, orang Bengal yang selalu menggoda, mengancam, dan terkadang menyerang mereka secara fisik.
Responden perempuan dan remaja putri menceritakan bahwa mereka sering diejek atau dilecehkan secara seksual oleh laki-laki masyarakat penampung terutama saat mengambil air dari lokasi yang jauh.
Pelaporan anonim merupakan instrumen yang penting untuk melaporkan pemerkosaan dan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual supaya mampu memberikan rasa aman bagi korban. Hasilnya, baik responden laki-laki maupun perempuan, tidak banyak mengetahui tentang layanan dukungan yang tersedia untuk kekerasan seksual dan berbasis gender.
Namun, kembali lagi pada permasalahan status tanpa kewarganegaraan, keadilan hukum hak asasi manusia memerlukan pengakuan dari pemerintah agar dapat melanjutkan pelaporan tersebut serta mendapat jaminan rasa aman bagi korban untuk melaporkan viktimisasi mereka.
Oleh karenanya, permasalahan pelik Rohingya memerlukan bantuan dari organisasi internasional dan berbagai negara demi prinsip kemanusiaan.
Kembali lagi kepada makna kekerasan seksual di atas, masyarakat dunia pun perlu menyuarakan isu kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, terutama kekerasan seksual terhadap perempuan.
Misalnya, upaya membangun awareness dan sikap non-judgmental dapat menjadi salah satu bentuk dukungan bagi korban kekerasan seksual Rohingya.
Selain itu, penyediaan layanan konsultasi bagi korban kekerasan seksual bisa menjadi salah satu upaya kecil yang memiliki dampak signifikan untuk memulihkan luka psikologis para korban.
Dengan demikian, bentuk dukungan dan membangun awareness dapat mendukung berjalannya layanan konsultasi tersebut.
Pada akhirnya, status tanpa kewarganegaraan Rohingya “menggerogoti” hak asasi manusia mereka. Kekerasan seksual Rohingya menjadi bukti nyata bahwa perempuan dapat menjadi senjata genosida suatu etnis.
Oleh karena itu, permasalahan pelik kekerasan seksual dan hak asasi manusia Rohingya membutuhkan dukungan dan bantuan dari masyarakat dunia atas nama kemanusiaan. (Z81)




