“Seng tak hapus malah (anggaran) Wali Kota dan Wakil Wali Kota kita hapus untuk mobil listrik. Timbange tuku mobil mending bangun pasar (daripada beli mobil mending buat membangun pasar),” – Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo
Politik merupakan sebuah istilah yang sejauh ini masih sulit ditafsirkan secara pasti. Ketidakpastian ini yang membuat politik dianggap sebagai dunia yang penuh dengan keburukan.
Padahal, politik itu penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Kebaikan yang ditunjukkan pemimpin kepada rakyat biasanya diperlihatkan dengan sikap setia kepada rakyat – bukan sebaliknya dengan rakyat yang harus setia pada seorang pemimpin.
Demikianlah arti kesetiaan dalam politik. Bukan berasal bawah tetapi harus dari atas ke bawah. Seorang politisi yang selalu setia bersama dan berjuang untuk rakyat dia tidak akan ditinggalkan.
Dan, demikian pula sebaliknya, seorang politisi yang tidak setia bersama rakyat dalam perjuangannya maka rakyat akan meninggalkannya begitu saja. Sederhana memang tapi berdampak luar biasa loh.
Nah, mungkin dilema kesetiaan semacam ini yang saat ini dihadapi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ketika menolak menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.
Gibran lebih memilih membangun pasar yang merupakan fasilitas publik dibandingkan mengganti kendaraan dinasnya, yakni Toyota Innova, yang menurutnya masih layak digunakan.
Anyway, sikap Gibran ini, oleh sebagian orang dianggap sebagai bentuk pembangkangan loh. Kok bisa?
Sedikit memberikan konteks, penggunaan mobil dinas listrik di lingkungan aparat pemerintah daerah merupakan salah satu ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.
Merespons aturan tersebut, Gibran mengatakan siap diberikan sanksi karena mengabaikan pengadaan mobil listrik yang telah diinstruksikan ayahnya sendiri, Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Franz Magnis-Suseno dalam bukunya Etika Jawa melihat ada nilai–nilai kesetiaan yang terbangun dalam budaya Jawa yang rupanya bersinggungan dengan konteks politik. Kesetiaan bukan hanya sikap menuruti, melainkan juga bagian dari bentuk legitimasi kekuasaan.
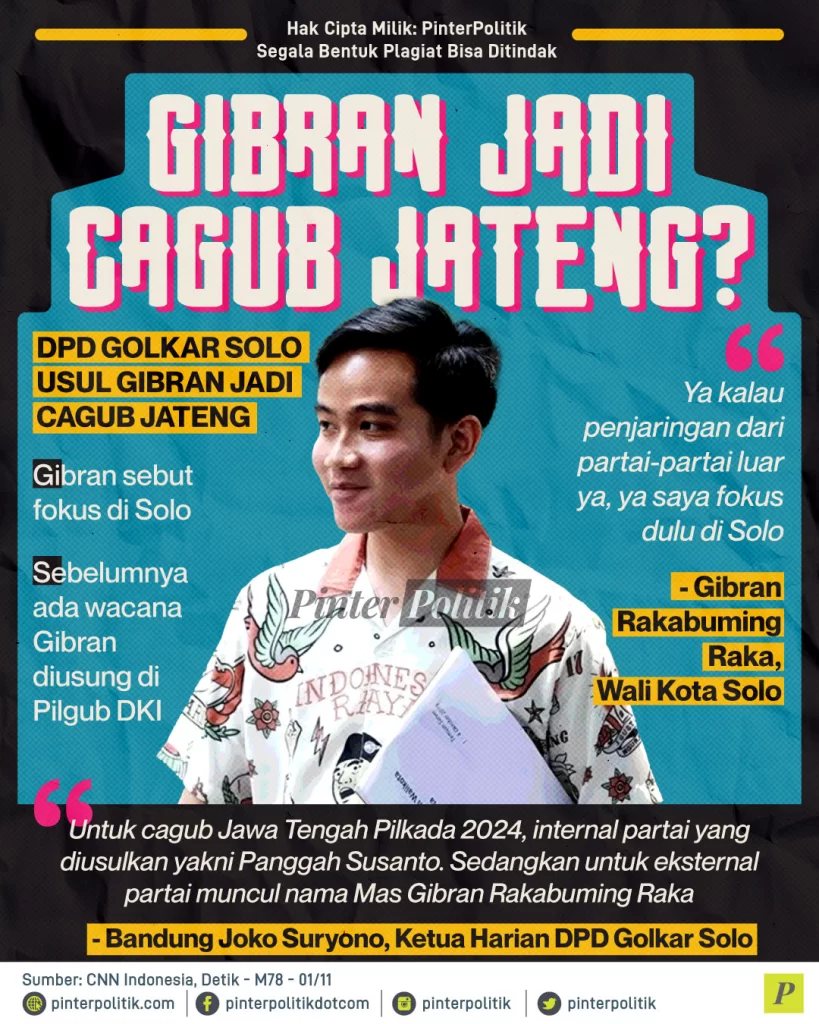
Nah, orang yang tidak setia dalam bahasa Jawa disebut mbalelo – artinya membangkang perintah atasan atau juga menentang arus.
Dalam cerita pewayangan, sikap “mbalelo” sering ditunjukkan sebagai memberontak, yang mana orang yang dianggap setia akhirnya memihak kepada musuh. Biasanya, sikap memberontak ini terjadi karena punya keyakinan sendiri akan suatu hal atau tidak puas dengan keadaan yang ada disekelilingnya.
Seperti halnya dalam cerita Ramayana versi wayang Jawa, dikisahkan adik Rahwana, yakni Gunawan Wibisana, yang “mbalelo” menyeberang dan memihak kubu Rama yang merupakan musuh dari kakaknya sendiri.
Bahkan, untuk mengembalikan istri Rama yang diculik Rahwana, Wibisana membuka rahasia kesaktian bala tentara Rahwana sehingga mereka dapat ditaklukkan.
Kembali ke konteks Gibran, sikap Gibran ini memperlihatkan realitas politik yang berbeda dengan kebanyakan kisah relasi kekuasaan antara ayah dan anak. Biasanya pengaruh Ayah begitu kuat, tapi Gibran dengan sikap “mbalelo”-nya ingin memperlihatkan bahwa ia mempunyai kemandirian politik yang perlu dihormati.
Well, terlepas dari pemaknaan istilah mbalelo yang sering ditafsirkan secara negatif karena dimaknai sebagai sikap membangkang, kita perlu hargai sebuah idealisme politik yang ditunjukkan Gibran.
Hal ini menunjukkan kalau, dalam politik, tidak selalu “kuasa” itu datang dari atas ke bawah tapi bisa sebaliknya.
Sebagai penutup, ngomong-ngomong soal pembangkangan, apakah mungkin pujian Gibran kepada Anies Baswedan yang diungkapkan beberapa waktu lalu bisa ditafsirkan sebagai kode kalau ia siap mbalelo? Who knows? Hehehe. (I76)





