Meski terdapat “disclaimer” bukan sebagai indikator sempurna, indeks Global Firepower (GFP) kerap diglorifikasi, menjadi justifikasi analisis, bahkan disebut menjadi landasan pembuatan kebijakan militer dan pertahanan Indonesia. Mengapa itu bisa terjadi?
Satu dari lima pesawat Hercules C-130J milik TNI AU telah diterima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada tengah pekan ini. Penambahan alutsista tersebut kemungkinan akan mengatrol posisi Indonesia dalam daftar negara dengan militer terkuat versi Global Firepower (GFP).
Mengacu data GFP di awal tahun 2023, kekuatan militer Indonesia berada di urutan ke-13 dari 145 negara di dunia. Salah satu indikatornya, diluar perhitungan C-130J anyar, Indonesia diperkuat 466 unit armada pesawat.
Sebagai penjabaran, Indonesia saat ini memiliki 176 unit helikopter, 15 di antaranya merupakan helikopter tempur. Selain itu, 127 unit pesawat latih dan 41 unit pesawat jet tempur, dengan 37 unit di antaranya berspesifikasi jet serang khusus juga kini tersebar di hanggar-hanggar TNI AU di seluruh Indonesia.
Selain kekuatan matra udara sebuah angkatan bersenjata, rilis militer terkuat GFP didasarkan pada lebih dari 60 indikator yang bermuara pada angka Indeks Kekuatan Negara (Nation’s Power Index atau PwrIndx).
Indikator tersebut mencakup jumlah personel militer, jumlah alutsista, posisi keuangan, kemampuan logistik, hingga karakteristik geografis.
Setiap tahun, GFP kerap menjadi tolok ukur diskursus militer dan pertahanan. Bahkan, data yang dikumpulkan kerap menjadi salah satu rujukan pembuatan kebijakan pertahanan.

Analis Pertahanan Fahmi Alfansi P Pane dalam publikasi berjudul Mengukur Kekuatan Militer mencatat, hingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 disusun, pemerintah masih mengutip GFP sebagai salah satu ukuran pencapaian pembangunan bidang keamanan dan ketertiban.
Pane menjabarkan, pada Tabel 9.2 lampiran Pidato Presiden RI yang disampaikan kepada DPR tanggal 16 Agustus 2021 lalu, tertera nilai indeks kekuatan militer Indonesia yang disadur dari GFP.
Selain menjadi rujukan pemerintah, skor dan peringkat GFP juga tak jarang menjadi glorifikasi sejumlah kalangan atas kekuatan militer dan pertahanan negara +62.
Dalam rilis terbaru 2023 misalnya, kekuatan militer Indonesia berada di atas Australia, Iran, Israel, hingga Vietnam.
Torehan itu kerap menjadi salah satu variabel yang menjadi justifikasi kebanggaan hingga “rasa cukup”, di mana bahkan ironisnya menjadi faktor untuk “menunda” progresivitas kebijakan militer dan pertahanan.
Meskipun indikatornya sekilas komplit, jika ditinjau lebih dalam lagi penggunaan skor indeks kekuatan militer dari GFP sesungguhnya tidak tepat. Mengapa demikian?
Kebanggaan Semu?
Di dalam situs GFP sebenarnya telah tertera bahwa material dari semua publikasi yang tersaji hanya untuk kepentingan historis dan entertainment value atau hiburan semata.
Kebijakan disclaimer itu sebenarnya cukup untuk tak menjadikan GFP sebagai rujukan utama, apalagi sebagai acuan perbaikan perangkat kerja, pemeliharaan, serta operasi militer dan pertahanan.
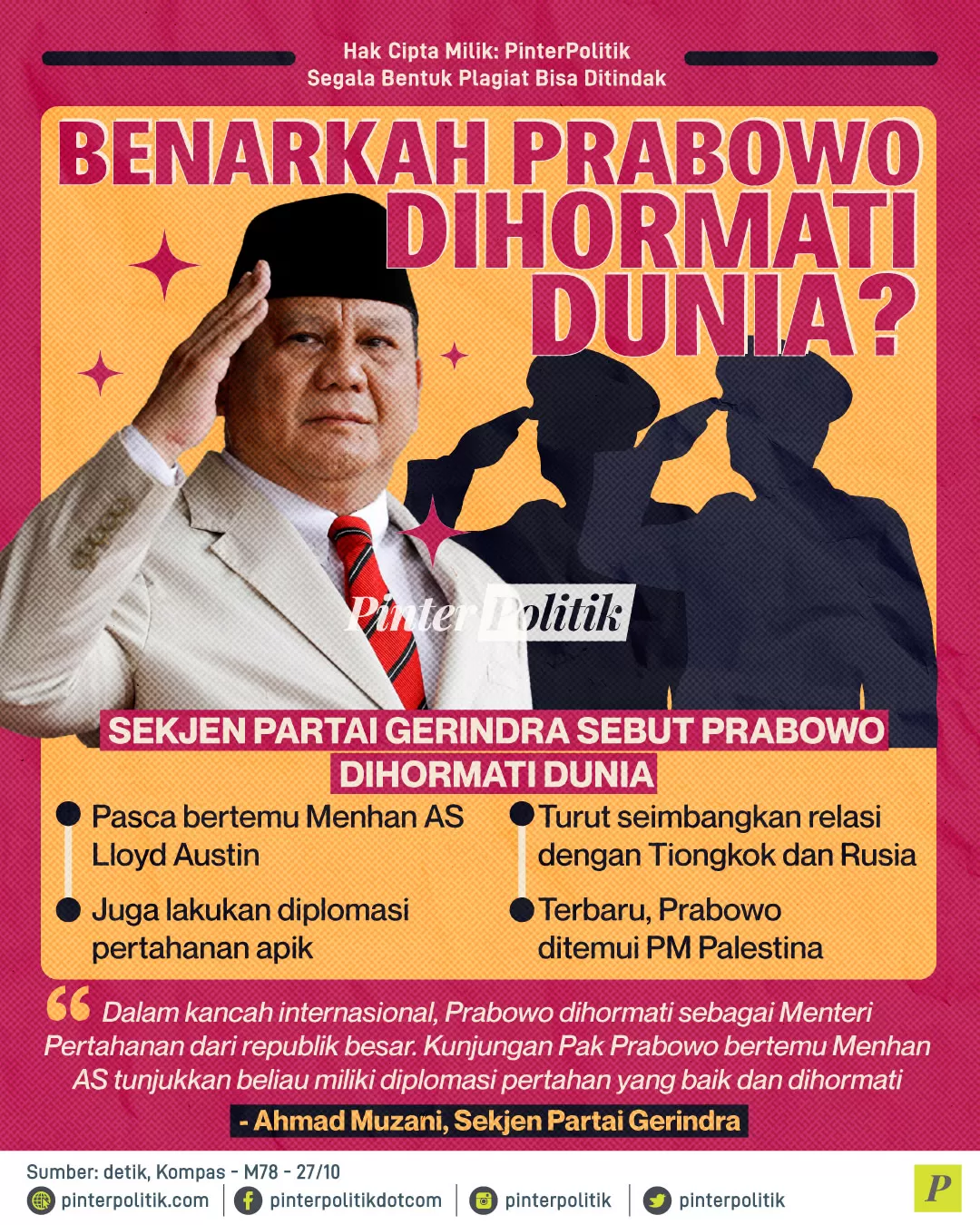
Maka dari itu, penggunaan secara luas bukan tidak mungkin mengindikasikan kecenderungan psikologis tertentu yang kurang tepat.
Martie Haselton, seorang Profesor psikologi asal University of California Los Angeles, dalam The Evolution of Cognitive Bias menjelaskan bias kognitif sebagai sebuah kesalahan secara sistematis dalam pola pikir yang berimplikasi pada tak rasionalnya penilaian serta keputusan yang dibuat, baik oleh individu maupun kelompok.
Secara lebih spesifik, apa yang terjadi pada fenomena kebanggaan GFP atau “GFP Pride” kiranya tergolong sebagai confirmation bias atau bias konfirmasi.
Raymond S. Nickerson dalam Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises menjelaskan bias konfirmasi sebagai kecenderungan untuk menafsirkan informasi yang hanya mendukung kebenaran serta keyakinan pribadi yang ia anggap paling benar. Bahkan, meskipun faktanya berkebalikan.
Selama ini, tak bisa dipungkiri antusiasme militer dan pertahanan Indonesia cukup besar. Setidaknya hal itu tampak di media sosial.
Literasi militer dan pertahanan kerap kali bias dengan kebanggaan aspek historis, perbandingan tak apple to apple, dan glorifikasi berdasarkan pemeringkatan serta penilaian yang tidak komprehensif.
Itu tampaknya diperparah dengan framing media yang parsial. Akibatnya, sejumlah kalangan tak jarang menganggap informasi yang selama ini diterimanya mengenai kekuatan militer dan pertahanan Indonesia sudah memadai.
Padahal, penilaian terhadap kekuatan angkatan bersenjata sebuah negara begitu kompleks dan berjalan sangat dinamis. Satu rujukan, dari GFP saja, misalnya, tak bisa serta merta dapat dijadikan landasan tunggal, terlebih menjadi sebuah kebanggaan semu.
Fahmi Pane pun melihat hal serupa. Terkait disclaimer di GFP misalnya, terdapat penjelasan aspek legal yang menyatakan tidak bertanggung jawab atas akurasi, ketepatan, kelengkapan, validitas, dan informasi terbaru dari semua informasi yang tersedia.
Dalam analisisnya mengenai GFP, Fahmi juga menguak Indonesia jamak diuntungkan secara kuantitas. Mulai dari jumlah penduduk, jumlah personel militer, panjang garis pantai, sumber daya alam, dan geografis.
Nyatanya, secara substansial dan kualitas, hal itu tak serta merta menggambarkan kondisi riil aspek operasional militer dan pertahanan.
Pada poin garis pantai misalnya, panjangnya garis pantai membuat Indonesia disebut sulit dikepung. Akan tetapi, Indonesia juga lebih sulit mengirimkan personel, alutsista, dan logistik secara cepat ke seluruh wilayah dengan realita itu.
Dari segi kuantitas juga demikian. Pemeringkatan GFP kerap hanya berdasarkan jumlah alutsista dan tak membedah lebih dalam mengenai kategori, kesiapan, dan kelengkapan sistem persenjataan.
Selain itu, terdapat satu hal nonteknis lain yang kiranya dapat menguak kualitas militer dan pertahanan Indonesia, yang sekaligus dapat menggugurkan catatan di dalam GFP. Apakah itu?

Silent Evidence Pertahanan?
Selain hanya berdasarkan kuantitas, pemeringkatan kekuatan militer dalam GFP dan proyeksi pertahanan selama ini kerap luput dari hal yang terabaikan atau istilah kerennya silent evidence.
Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable menjelaskan soal bahaya silent evidence atau bukti bisu yang kerap dilupakan ketika menyimpulkan sesuatu.
Untuk melihat peristiwa terdapat banyak faktor penentu. Penegasan itu adalah upaya untuk menolak doktrin monokausalitas. Penilaian terhadap sebuah aspek perlu dan harus memikirkan bahwa hal itu ditentukan secara secara multikausalitas, termasuk faktor perilaku dan dinamika interaksi manusia sebagai instrumen utama di dalamnya.
Multikausalitas sendiri adalah konsep yang menegaskan bahwa dalam sebuah peristiwa, baik politik, sejarah, dan sosial memiliki rangkaian kausalitas yang tidak sederhana dan tunggal. Dan yang terpenting, sering kali ada silent evidence yang tidak diketahui atau diabaikan.
Ini yang kemudian disebut sebagai bukti bisu. Bukan tidak mungkin, kesimpulan atas sebuah subjek selama ini bertumpu pada informasi yang begitu kecil. Padahal, terdapat bukti-bukti yang mungkin tidak pernah diketahui atau “diabaikan”.
Dalam konteks penilaian dan proyeksi kebijakan pertahanan, konteks yang tidak statis dalam pembangunan pertahanan dan perencanaannya juga menentukan. Mulai dari ketersediaan anggaran, dinamika lingkungan strategis, birokrasi, hingga faktor politik.
Selain jenis dan teknologi alutsista yang terus berkembang, kemampuan alutsista dan awaknya, kesiapan tempur, logistik, interoperabilitas, keberpihakan sekutu pertahanan, serta moral prajurit kiranya juga menjadi silent evidence yang tak jarang luput dari kalkulasi.
Belum lagi soal birokrasi dan aspek politik. Selama ini, porsi anggaran pertahanan Indonesia kerap “berdesakan” dengan alokasi dan prioritas kementerian lain, plus political will para aktor terkait.
Akibatnya, perencanaan pertahanan yang telah disusun matang dan sesuai tantangan kontemporer tak jarang meleset dari target. Satu ekses yang muncul kemudian adalah pengadaan alutsista dengan mengandalkan pinjaman luar negeri.
Itu pun tidak menutup kemungkinan akan berkonsekuensi secara politik di kemudian hari.
Oleh karena itu, GFP seharusnya tidak dijadikan tolok ukur buta atas aspek pertahanan, jadi kebanggaan semu, terlebih menjadi landasan kebijakan militer dan pertahanan Indonesia.
Penilaian secara komprehensif dengan keberanian memasukkan berbagai silent evidence determinan dalam aspek militer dan pertahanan juga diharapkan dilakukan para pemangku kebijakan terkait. (J61)




